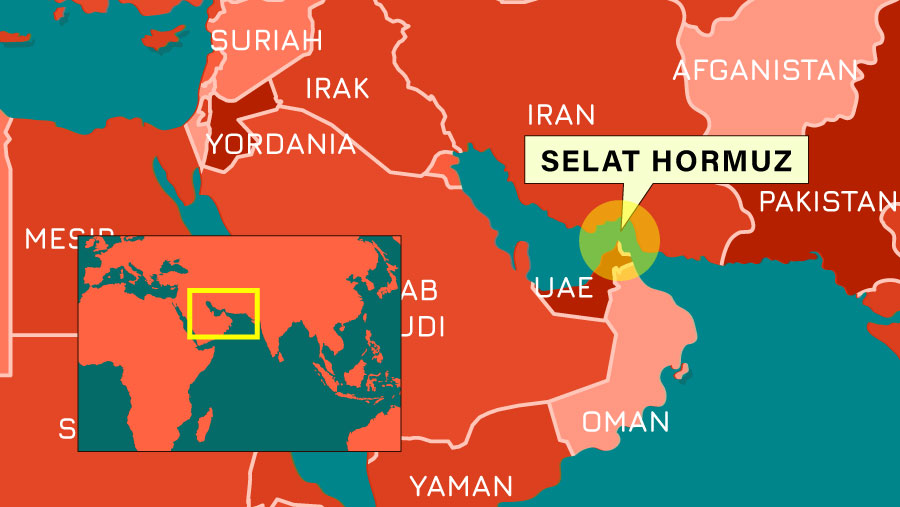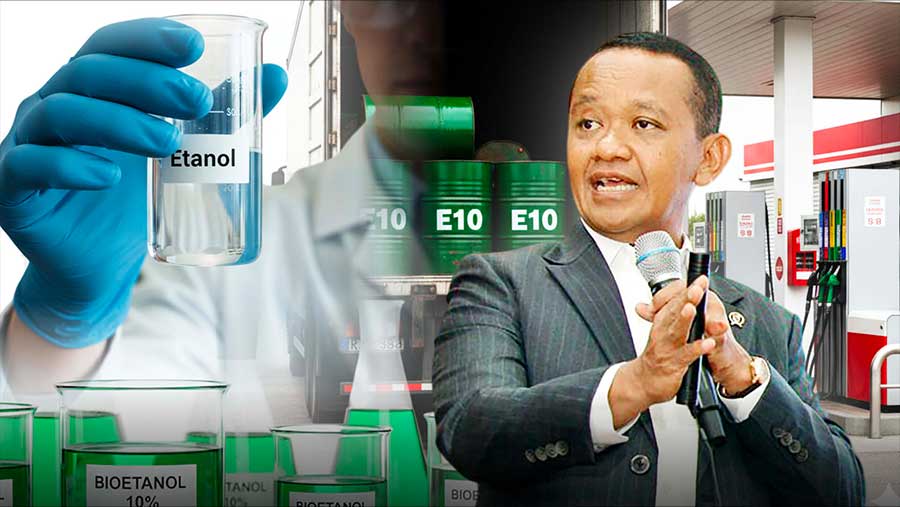"Walaupun demikian, tadi saya sampaikan potensinya mungkin tidak terlalu besar. Mengingat dominasi dari negara-negara besar terutama Amerika," ujarnya.
Selain akses politik, Dafri melihat keikutsertaan Indonesia juga bisa dibaca sebagai strategi perlindungan kepentingan nasional, terutama dari tekanan AS. Menurutnya, bergabung ke dalam dewan tersebut dapat menjadi bentuk hedging strategy agar Indonesia tidak menjadi sasaran tekanan ekonomi, politik maupun keamanan.
"Yang kedua mungkin bayangannya ketika kita masuk di situ mungkin kita menghindari menjadi target dari Amerika, terutama berhubungan dengan bidang ekonomi, politik, keamanan semua. Dengan masuk ke situ kita melindungi diri gitu ya. Dari bidang perdagangan misalnya, mungkin kita tidak dikenai tarif yang tinggi," jelas Dafri.
"Di bidang politik mungkin kita tidak akan dianggap musuh. Dalam keamanan kita tidak menjadi target seperti Iran atau Venezuela atau macam-macam. Bagi negara ancamannya itu luar biasa, jadi mungkin itu menghindari," lanjutnya.
Namun, keuntungan itu harus dibayar mahal. Dafri menyoroti dampak langsung terhadap citra Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negeri bebas dan aktif, serta konsistensi sikap pro-Palestina.
"Salah satu dampak yang langsung dirasakan yaitu citra kita sebagai negara 'non-blok'. Politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian pro-Palestina, itu bisa terhapus dengan masuknya kita menjadi anggota dewan perdamaian bentukan Trump ini, terutama di mata bangsa-bangsa atau negara-negara yang selama ini ya sealiran dengan kita seperti negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam, negara-negara Global South misalnya ya," kata Dafri.
Ia juga mengingatkan bahwa inisiatif Trump sendiri tidak sepenuhnya didukung sekutu tradisional Amerika. Sejumlah negara Eropa bahkan bersitegang dengan Washington.
"Artinya, maksud saya kerugian kita adalah ketika masuk ke situ loh berarti kita terperangkap pada negara yang dimusuhi oleh banyak orang. Yang justru yang musuh itu adalah negara yang selama ini dianggap aliansi natural dari Amerika, tiba-tiba kita masuk ke situ," ujarnya.
Dari sisi hukum internasional, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai Indonesia nyaris tidak memiliki pilihan lain selain bergabung. Ia mengacu pada ancaman tarif yang kerap digunakan Trump terhadap negara yang menolak inisiatifnya.
"Ada preseden di mana Presiden Prancis menolak bergabung dan Trump mengancam tarif 200%," ungkap Hikmahanto.
Namun, ia menyoroti biaya keanggotaan yang sangat besar, mencapai US$1 miliar, yang dinilainya tidak sebanding jika Indonesia tidak memiliki suara signifikan.
"Jumlah ini sangat besar, terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel untuk kemerdekaan Palestina," bebernya.
Hikmahanto juga mempertanyakan legitimasi dan tata kelola Dewan Perdamaian tersebut. Menurutnya, statuta atau piagam pendirian dewan tidak jelas, sementara Trump memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan.
"Trump adalah pemilik suara tunggal dalam pengambilan keputusan. Pengurus harian sudah diumumkan dan semua atas penunjukan Trump, termasuk pengurus untuk Gaza. Kalau Indonesia harus membayar mahal dan Indonesia tidak bisamenempaktkan orangnya, sungguh sangat disayangkan," kata Hikmahanto.
Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam, Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy, memandang langkah Indonesia perlu dibaca secara pragmatis dan strategis. Dalam dunia internasional yang makin transaksional, kehadiran di forum yang dekat dengan pusat kekuasaan dinilai tetap penting.
"Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia bukan bentuk legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh," kata Umam.
Ia menilai isu Palestina selama ini justru menuntut Indonesia mencari kanal baru di luar mekanisme multilateral yang melemah.
"Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki peluang, meski terbatas, untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi menjadi sekadar urusan keamanan Israel semata," ujarnya.
Namun, Umam menegaskan keikutsertaan ini hanya bermakna jika Indonesia bersikap aktif dan substantif, bukan simbolik. Ia menyebut Indonesia harus konsisten membawa kerangka hukum internasional, membangun koalisi negara middle powers, serta mendorong langkah konkret seperti gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa syarat.
Dalam konteks politik luar negeri bebas-aktif, Umam menilai langkah ini masih bisa dibenarkan.
"Bebas-aktif bukan berarti menjauhi forum yang tidak ideal, melainkan hadir secara aktif untuk membela prinsip, sambil tetap bebas dari ikatan blok dan agenda sempit kekuatan besar," paparnya.
Meski begitu, ia mengingatkan partisipasi Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap tegas terhadap pendudukan dan pelanggaran hukum humaniter.
"Jika dikelola dengan cermat, langkah ini dapat memperluas kanal perjuangan Palestina di tengah melemahnya multilateralisme, sekaligus menegaskan bahwa politik luar negeri bebas-aktif Indonesia tetap relevan di dunia yang semakin keras dan tidak ideal," tukas Umam.
(del/hps)