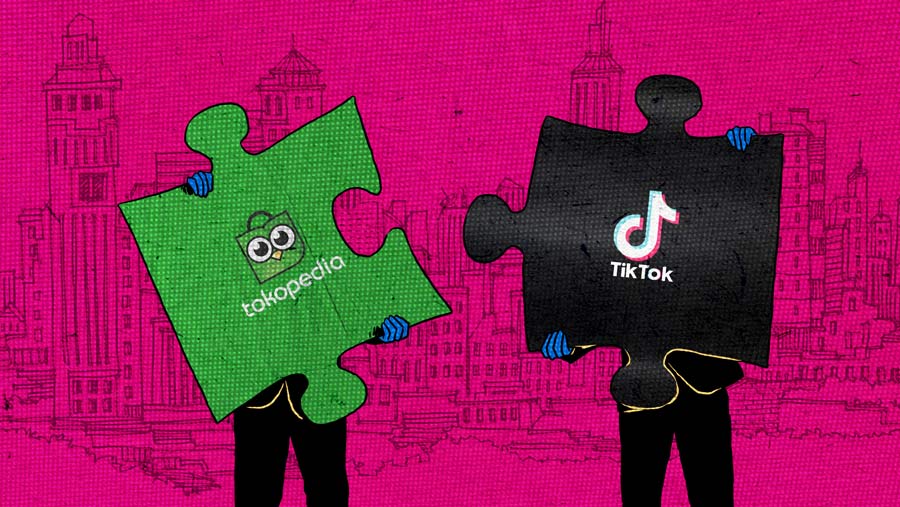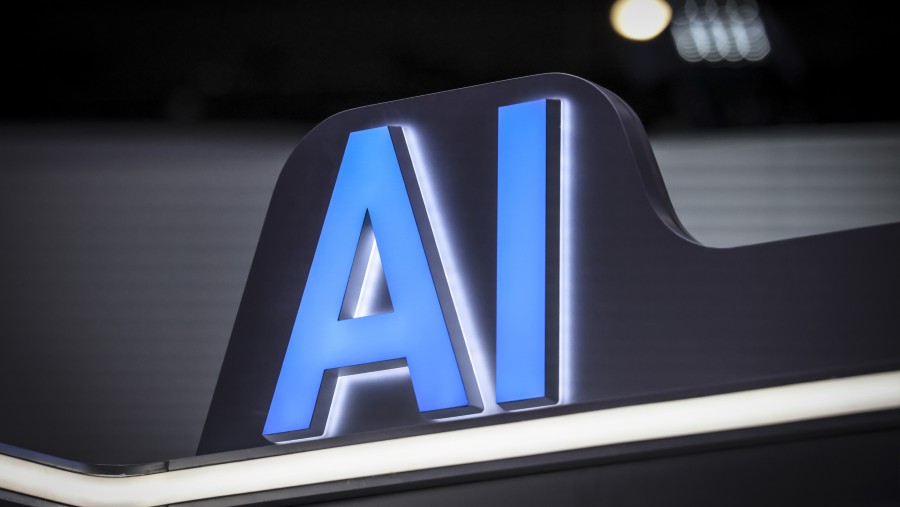Perlukah Perang Harga Dilarang?
Rionanda Dhamma Putra
27 October 2025 08:16

|
Penulis: Rionanda Dhamma Putra Rionanda Dhamma Putra adalah Treasury Economist Bank Danamon Indonesia sejak Desember 2024. Pribadinya adalah seorang pembelajar yang ingin tahu banyak hal. Lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2023, minatnya berkutat pada ekonomi politik, ekonomi regional, dan keuangan. |
Pohon yang menggugurkan daun di musim semi. Kiasan itu barangkali tepat untuk menggambarkan industri otomotif Indonesia saat ini. Di tengah sinyal pemulihan ekonomi yang masih terbatas, segmen roda empat “menggugurkan daun” yang paling banyak.
Data GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 559.334 unit, turun 11,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (663.660 unit).
Penurunan ini dipicu oleh tiga hal utama. Pertama, pelemahan harga komoditas ekspor (kecuali sawit) yang menggerus pendapatan sektor hulu. Kedua, menurunnya daya beli domestik, dengan Indeks Pendapatan Konsumen BI tercatat di 115,0 (turun 9,6% sejak awal tahun) dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja merosot tajam ke 92,0 (turun 14,5%). Ketiga, perubahan lanskap persaingan yang membuat konsumen semakin menahan belanja.
Baca Juga
Suaka Pertumbuhan Baru
Pada saat yang sama, panggung otomotif Indonesia sedang kedatangan “tamu” dari Tiongkok. Fenomena price war atau Neijuan yang mengguncang pasar mobil di sana kini mulai terasa di sini. Pemotongan harga masif oleh sejumlah pabrikan, terutama merek Tiongkok di ajang GIIAS 2025, menjadi sinyalemen jelas. Lantas, mengapa perang harga justru terjadi saat daya beli masyarakat sedang melemah?

Jawabannya ada di negeri asalnya. Sejak 2023, Tiongkok mengalami kompetisi harga yang ekstrem lintas sektor, terutama di ritel dan otomotif, seiring tekanan daya beli domestik. Kendaraan energi baru (new energy vehicles / NEV) menjadi motor utama perang harga ini, didorong insentif pemerintah. Pada Agustus 2023, pabrikan NEV mulai menurunkan harga besar-besaran untuk menyaingi kendaraan konvensional, terutama di segmen pekerja kerah biru dan taksi daring (Reuters, 2023). Pada 2024, kompetisi itu meluas menjadi antar sesama pabrikan NEV, hingga akhirnya BYD menurunkan harga hingga 30% untuk 22 model pada Mei 2025 (Reuters, 2025).
Langkah agresif ini membuat marjin industri menipis dan memicu intervensi Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) Tiongkok, yang memerintahkan penghentian praktik perang harga ekstrem. Sejak saat itu, ekspor menjadi pelarian baru alias “suaka pertumbuhan” bagi pabrikan Tiongkok untuk menjaga volume penjualan.
Posisi Indonesia di Peta
Menariknya, larangan perang harga di Tiongkok pada Juni 2025 bertepatan dengan “musim semi” otomotif di Indonesia, yakni periode Juli. Bulan ini menjadi momen tahunan peluncuran model baru. Pabrikan Tiongkok pun melihat peluang emas: Pasar besar, siklus waktu peluncuran yang tepat, dan jarak geografis yang dekat.
Hasilnya, sepanjang Juli 2025 terdapat 11 peluncuran mobil baru, di mana enam di antaranya merupakan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Meski lebih sedikit dibanding 14 model BEV pada Juli 2024, dampaknya terhadap harga sangat terasa. Hampir semua model baru adalah volume makers, memaksa pabrikan eksisting menurunkan harga jualnya secara signifikan.
Jika dibandingkan dengan Tiongkok, tahap perang harga di Indonesia berlangsung lebih cepat. Model baru bersaing di dua arena sekaligus: Antara sesama BEV dan dengan kendaraan konvensional (ICE) di segmen harga yang sama. Percepatan ini terjadi karena ruang kebijakan dan finansial pabrikan Tiongkok untuk memotong harga di dalam negeri sudah semakin sempit.
Senja Hadir Tanpa Dipaksa
Namun, ada kemungkinan bahwa perang harga ini akan mereda secara alami tanpa intervensi. Laporan keuangan pabrikan otomotif Tiongkok pada kuartal II 2025 menunjukkan marjin yang terus tergerus, hanya terselamatkan oleh ekspor. Di sisi lain, rantai nilai industri otomotif Tiongkok dalam baterai dan perakitan tertekan oleh penurunan investasi modal (capex).
Dari sisi kebijakan, insentif pajak untuk kendaraan listrik impor (CBU BEV) akan berakhir pada Desember 2025. Berakhirnya insentif ini akan menaikkan harga sejumlah model dan menurunkan intensitas peluncuran baru. Fokus industri akan bergeser dari volume of launch menjadi volume of sales.
Kedua faktor tersebut akan menjadi penahan alami, membuat senja perang harga hadir dengan sendirinya. Namun, pekerjaan rumah kita belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menarik dan memperluas rantai nilai otomotif global, khususnya dari Tiongkok agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi menjadi bagian dari pusat produksi Asia.
DISCLAIMER
Opini yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap, kebijakan, atau pandangan resmi dari Bloomberg Technoz. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau validitas informasi yang disajikan dalam opini ini.
Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan verifikasi dan mempertimbangkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan berdasarkan opini yang disampaikan. Jika terdapat keberatan atau klarifikasi terkait isi opini ini, silakan hubungi redaksi melalui contact@bloombergtechnoz.com
Tentang Z-ZoneZ-Zone merupakan kanal opini di Bloomberg Technoz yang menghadirkan beragam pandangan dari publik, akademisi, praktisi, hingga profesional lintas sektor. Di sini, penulis bisa berbagi ide, analisis, dan perspektif unikmu terhadap isu ekonomi, bisnis, teknologi, dan sosial. Punya opini menarik? |
(rio)