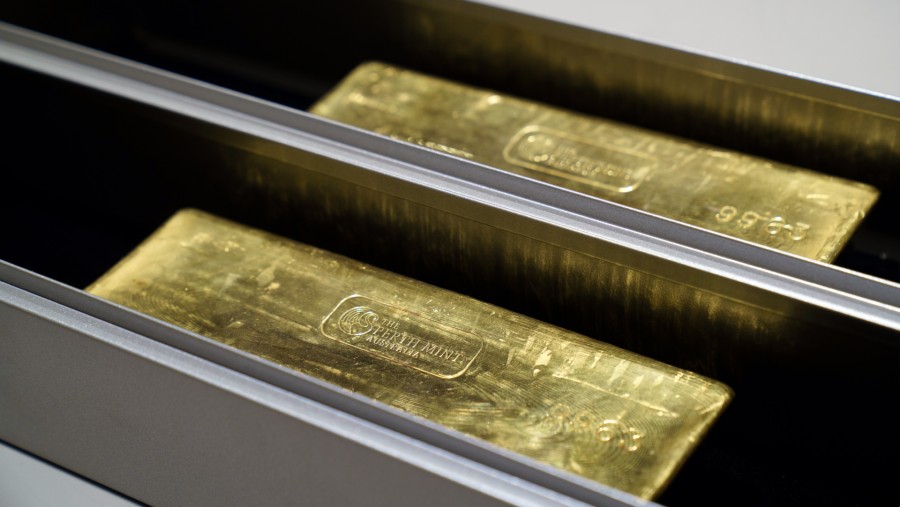Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah masih terus terjadi, terutama di pasar forward, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran investor terhadap ketangguhan kebijakan domestik di tengah volatilitas global.
Di balik kekhawatiran ini, pasar juga menangkap adanya tanda kebijakan fiskal-moneter yang tidak sejalan beriringan. Kebijakan fiskal terus ekspansif dengan menggenjot belanja, melakukan berbagai stimulus fiskal, hingga mengguyur pasar dengan likuiditas yang cukup deras.
Akan tetapi di sisi lain, pada saat yang sama Bank Indonesia (BI) justru terlihat tergopoh-gopoh menjaga stabilitas rupiah dan menahan risiko yang bisa terus melebar. Pasar obligasi agaknya tengah merespons ketidaksinkronan ini, sehingga permintaan yield di surat utang jangka pendek cenderung melebar.
Sementara dari pasar obligasi AS, yang jadi jangkar sistem keuangan dunia, juga menunjukkan pola sejenis. Di saat pasar yakin kalau The Fed akan memangkas suku bunga dalam beberapa bulan ke depan, yield US Treasury malah naik.
Misalnya, tenor 10 tahun naik 3,7 bps menjadi 4,14%, tenor 30 tahun naik 3,7 bps ke 4,79%, dan tenor 2 tahun naik 3,8 bps ke 3,56%.
Lantas, apa yang sedang terjadi?
Jim Bianco, Presiden Bianco Research, mengatakan bahwa saat ini investor cenderung cemas terkait rencana The Fed menurunkan suku bunga sementara inflasi belum benar-benar disiplin berada di dekat target 2%.
“Pasar benar-benar mengkhawatirkan arah kebijakan tersebut (yang dianggap sudah terlalu jauh),” kata Bianco, sebagaimana dikutip Bloomberg News.
Investor takut The Fed melonggarkan kebijakan moneter terlalu cepat. Kalau itu terjadi, maka pasar perumahan AS bisa kembali panas dan mengalami kenaikan suku bunga. Kita semua tahu bahwa hal itulah yang memicu krisis keuangan global 2007-2008.
Melansir Bloomberg News, pasar obligasi AS cenderung tidak percaya pada gagasan Presiden AS Donald Trump bahwa pemangkasan suku bunga yang lebih agresif akan membuat yield obligasi turun dan pada gilirannya menurunkan bunga KPR, kartu kredit, dan berbagai jenis pinjaman lainnya.
Saat ini, ada ketegangan yang melampaui kebijakan ekonomi, yaitu intervensi politik terlalu dalam. Kekhawatiran kian meningkat bahwa Trump, yang selama masa jabatannya dulu sering mengkritik The Fed, kini punya peluang besar menekan bank sentral untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga.
Nama Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, digadang-gadang akan menggantikan Jerome Powell sebagai The Fed-1 pada Mei nanti. Dengan naiknya Hassett yang memiliki relasi dekat dengan Donald Trump, beberapa kalangan mengkhawatirkan independensi bank sentral AS.
Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas mengatakan, pasar mulai mempertimbangkan kondisi ketidakpastian ini, termasuk adanya potensi kekosongan atau jeda hingga Juni 2026 saat Gubernur The Fed yang baru mulai menjabat.
Sentimen ini juga yang kemudian mendorong kenaikan yield UST, bahwa saat ini pasar tidak cuma membaca data ekonomi, tetapi juga membaca arah politik. Saat politik masuk terlalu dalam ke ruang kebijakan moneter, pasar cenderung kesulitan memprediksi arah, dan yang terjadi pasar akan meminta harga lebih dari ketidakpastian yang ditawarkan pemerintah atau aktor politik.
Yield Membesar, Rupiah Tertekan?
Dengan UST cenderung bearish dan risiko global meningkat, investor memilih mengurangi durasi atau menahan pembelian di tenor panjang. Hasilnya, pergerakan flat pada INDON dan bearish flattening pada SUN domestik.
Sementara itu, rupiah masih dalam tekanan dan pasar memperkirakan depresiasi bertahan di rentang Rp16.650-16.750/US$ dalam sepekan ke depan. Pasar tampaknya sedang menunggu hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 10 Desember sebelum mengambil posisi yang lebih agresif.
“Kami memperkirakan yield SUN 10 tahun bergerak flattish di kisaran 6,2-6,25%, sementara INDON 10 tahun berada di kisaran 4,9-4,95%.” kata Lionel.
Agaknya pasar sedang menunggu kepastian, bukan sekadar mengenai dipangkas atau tidaknya tingkat suku bunga, tetapi juga mengenai arah kebijakan dalam arti yang lebih luas, baik domestik maupun global.
Di tengah dinamika yang penuh ketidakpastian ini, ada dua hal penting yang bisa dicermati. Pertama, yield bergerak tidak searah dengan narasi kebijakan, jadi tanda bahwa pasar bisa jadi sedang meragukan sinkronisasi kebijakan fiskal–moneter.
Kedua, politik kini menjadi variabel yang tak bisa diabaikan, terutama di AS. Ketika AS terguncang oleh ketidakpastian kebijakan, pasar negara berkembang seperti Indonesia pasti terkena imbasnya.
Terlebih di Indonesia sendiri juga terjadi hal yang sama. Adanya perbedaan pandangan antara pemangku kebijakan fiskal dan moneter membuat pasar menimbang secara cermat dan cenderung bersikap ekstra hati-hati.
Seperti pada awal pekan lalu, BI membatalkan lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di tengah permintaan yang mencapai Rp38,72 triliun. Tanpa adanya publikasi dan penjelasan resmi, pasar menangkapnya sebagai sinyal ketidaksinkronan antara pemangku kebijakan fiskal-moneter.
Pembatalan ini ditangkap pasar sebagai respons atas pernyataan Menteri Keuangan yang menyoroti bahwa terjadi penyerapan uang lebih melalui SRBI yang membuat uang beredar tumbuh melambat. Untungnya, pada Jumat (5/12/2025) pengunguman lelang ini terbit juga dengan total pemenangan Rp24.460 miliar.
Setidaknya, pasar saat ini menantikan koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter, untuk memberikan sinyal yang konsisten. Sebab, pasar tidak dapat menerima ketidakjelasan arah kebijakan lantaran adanya tekanan politik.
Seperti yang terjadi di AS, hasilnya sudah terlihat, kala The Fed memangkas suku bunga, tetapi yield malah turun lantaran pasar meragukan independensinya.
Indonesia sepertinya belum sampai ke titik itu. Namun, sinyal di pasar sudah menangkap ke arah sana. Pembatalan lelang SRBI dan kritik terbuka Menteri Keuangan sebagai pengampu kebijakan fiskal terhadap BI sebagai pemangku kebijakan moneter tengah menggoyang persepsi pasar.
(riset/aji)