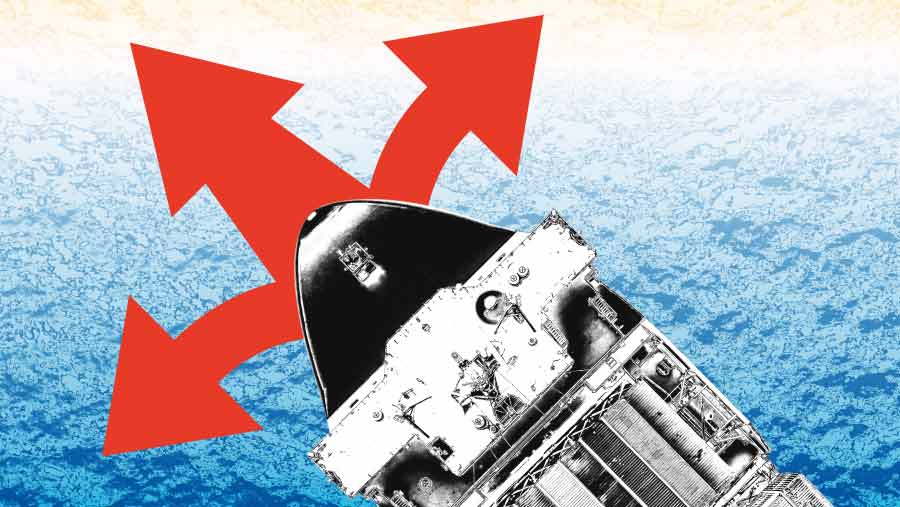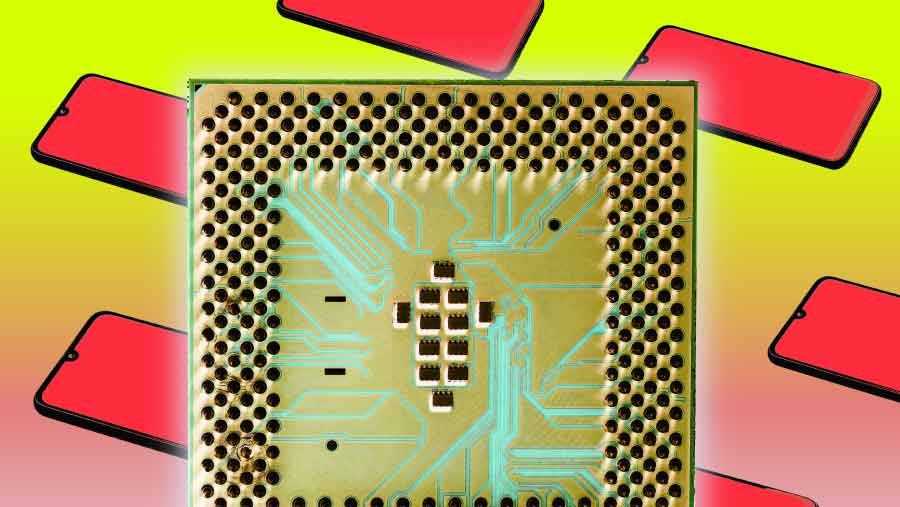Namun, kita tidak bisa menyederhanakan pelemahan rupiah semata sebagai “dampak global” dan menutup mata terhadap persoalan struktural di dalam negeri.
Defisit fiskal yang mencapai 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, hampir menyentuh ambang batas atas 3% PDB, menggambarkan posisi keuangan negara yang kian sempit. Kondisi ini pun membuat pelaku pasar khawatir terhadap kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara dan berdampak pada pelemahan rupiah di mata investor asing.
Biaya Produksi Naik, Usaha Terjepit
Bagi sektor riil, pelemahan rupiah adalah kabar buruk. Mayoritas produsen dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor.
Dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, mereka harus menanggung biaya produksi yang lebih mahal. Sebab, mereka membeli barang dalam kurs dolar AS dan menjual produknya di dalam negeri dengan kurs rupiah.
Kenaikan biaya ini sering kali tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke konsumen karena lemahnya permintaan domestik dan penurunan daya beli yang sedang terjadi. Alhasil, margin usaha bisa tergerus, dan berimbas pada tertundanya ekspansi usaha.
Ekspansi usaha tertunda, akibatnya ekonomi juga melemah, dan lapangan kerja yang seharusnya mungkin dibuka menjadi tak tersedia.
Kembali lagi ke soal biaya produksi, biasanya sektor pangan menjadi pelaku usaha yang mudah terpukul oleh fluktuasi kurs. Ketergantungan produsen pada impor gandum, kedelai, gula, dan bahan pakan ternak membuat pelemahan rupiah cepat tercermin pada harga pangan.
Produsen menghadapi kenaikan biaya, sementara konsumen menghadapi harga yang semakin tak terjangkau. Inflasi pangan yang bersumber dari nilai tukar (imported inflation) ini akan sulit dihindari.
Sebagai catatan, melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor barang konsumsi pada 2025 mencapai US$20,01 juta setara dengan Rp336,16 miliar. Sementara impor bahan baku nilainya US$153,19 juta setara dengan Rp2,57 triliun.
Setiap tahun, total impor barang konsumsi mengalami kenaikan. Pada 2023, nilainya naik 8,7% dari US$19,83 juta dolar pada 2022, menjadi US$21,55 juta. Begitu juga dari 2023 ke 2024 naik 5,4% dari US$21,55 juta menjadi US$22,73 juta.
Sedangkan, nilai total impor bahan baku setiap tahun juga mengalami kenaikan 5,41% pada 2024 menjadi US$170,71 juta dari US$161,95 juta pada 2023. Sementara, data 2025 nilainya mencapai US$153,19 juta belum termasuk data impor di Desember.
Impor barang konsumsi terdiri dari produk siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dalam bentuk makanan dan minuman, elektronik, kendaraan bermotor, pakaian dan sepatu, serta buah-buahan dan sayuran, serta produk plastik dan produk perawatan diri.

Sementara, impor bahan baku merupakan bahan mentah maupun setengah jadi yang dipakai untuk produksi seperti bahan pangan mulai dari daging, gula, kedelai, gandum, hingga produk non-pangan seperti plastik, suku cadang kendaraan, dan bahan bakar minyak.
Dengan tingkat ketergantungan impor yang tinggi, bukan hanya industri yang terdampak tapi juga usaha kecil dan menengah (UKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. UKM berada pada posisi paling rentan dibanding industri yang umumnya sudah memiliki sistem hedging atau mekanisme lindung nilai terhadap dolar.
UKM tak memiliki hal itu. Tanpa lindung nilai dan dengan akses pembiayaan yang terbatas, UKM harus menanggung fluktuasi kurs ini secara langsung. Di sinilah pelemahan rupiah berpotensi menggerus ketahanan ekonomi di bawah.
Daya Beli Menurun
Pelemahan rupiah juga berdampak pada daya beli rumah tangga. Harga kebutuhan pokok meningkat, ongkos transportasi membengkak lantaran kenaikan harga bahan bakar, dan biaya hidup kian menekan.
Sedangkan, pertumbuhan upah seringkali tertinggal dari laju kenaikan harga. Akibatnya, daya beli melemah, dan ruang konsumsi semakin menyempit, terutama bagi rakyat yang mayoritas bekerja di sektor informal.
Baru-baru ini, Bank Indonesia merilis data penjualan ritel. Meski ada kenaikan, tetapi tak cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara solid.
Mengacu data penjualan ritel BI yang rilis pada Senin (12/1/2026), pertumbuhan penjualan ritel ditopang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta suku cadang dan aksesori kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga menguat bukan karena adanya peningkatan kesejahteraan, tapi karena kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
Pada saat yang sama, penjualan barang tahan lama justru turun. Penjualan peralatan informasi dan komunikasi naik 13,9% secara bulanan, tetapi terkontraksi sebesar 27,4% secara tahunan.
Sebagai gambaran, barang tahan lama terdiri dari penjualan telepon selular, kendaraan bermotor, dan barang elektronik lainnya. Bahkan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sempat merevisi target penjualan mobil untuk 2025 dari sebelumnya 900.000 unit menjadi 780.000 unit.

Penjualan kendaraan, sebagai barang bernilai besar dan termasuk dalam komponen durable goods seringkali jadi barometer perekonomian lantaran berada di titik temu antara daya beli masyarakat, dan ketersediaan pembiayaan.
Turunnya angka penjualan barang tahan lama secara tahunan, menjadi sinyal bahwa rumah tangga justru sedang menahan belanja besar dan memilih mempertahankan uang daripada membelanjakannya di luar kebutuhan dasar.
Meski pemerintah menggelontorkan likuiditas sebesar Rp276 triliun, tetapi tak lantas membuat masyarakat mengambil pinjaman untuk membiayai barang konsumtif yang sifatnya tersier seperti kendaraan bermotor yang tentu tak jadi prioritas di masa-masa ekonomi seperti sekarang ini.
Dampak Terhadap Rakyat Kecil
Bukan hanya daya beli kelas menengah yang tergerus oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, tapi juga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pangan dan energi menyerap porsi terbesar dari pendapatan bulanan mereka. Ketika harga pangan seperti beras, minyak goreng, atau kenaikan biaya transportasi akibat harga bahan bakar naik, mereka tak punya ruang cukup untuk menyesuaikan konsumsi tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Tak seperti kelas menengah yang bisa memotong anggaran liburan, atau menunda pembelian kendaraan bermotor sampai kondisi ekonomi mulai stabil.
Inflasi yang diakibatkan oleh pelemahan rupiah dapat menghantam kelompok bawah paling berat. Jika kelompok menengah dan atas punya opsi untuk menabung, menunda konsumsi, atau beralih ke produk substitusi yang lebih terjangkau, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tetap menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan yang tak bisa mereka tunda.
Hal ini membuat setiap kenaikan dolar AS yang memicu kenaikan harga pangan semakin memperlebar ketimpangan daya beli. Meski seringkali pemerintah menyalurkan bantuan sosial, tetapi sifat bantuan itu sementara, dan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup yang bersifat permanen.
Kondisi struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor ini membuat penguatan dolar AS seolah jadi “pajak tak terlihat”, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga, saat dolar AS menguat dan rupiah menurun, masyarakat harus membayarnya, bukan dengan tagihan resmi dari negara, tapi dari menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah, dan isi piring masyarakat kelas bawah yang semakin susut.
(riset/aji)