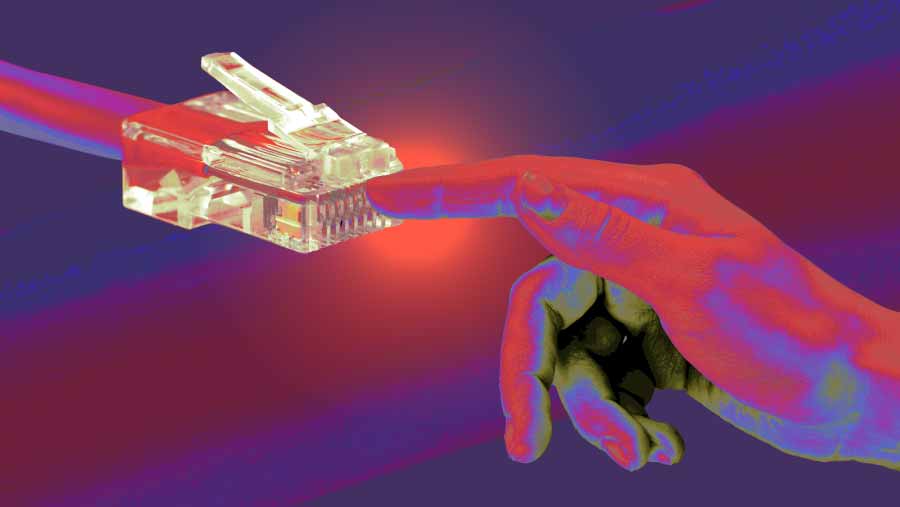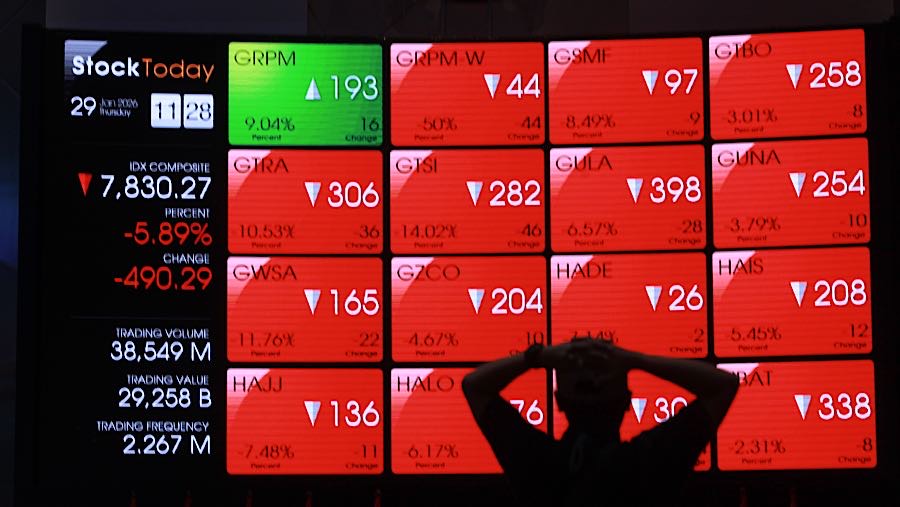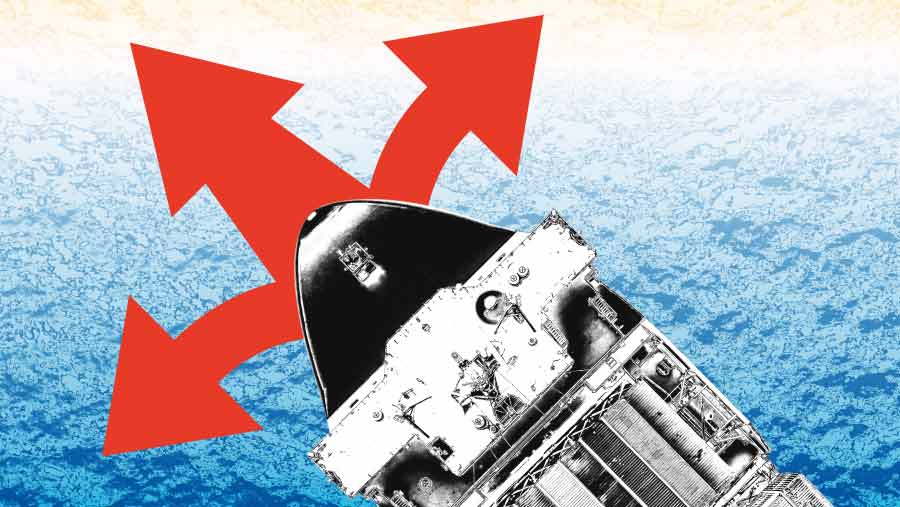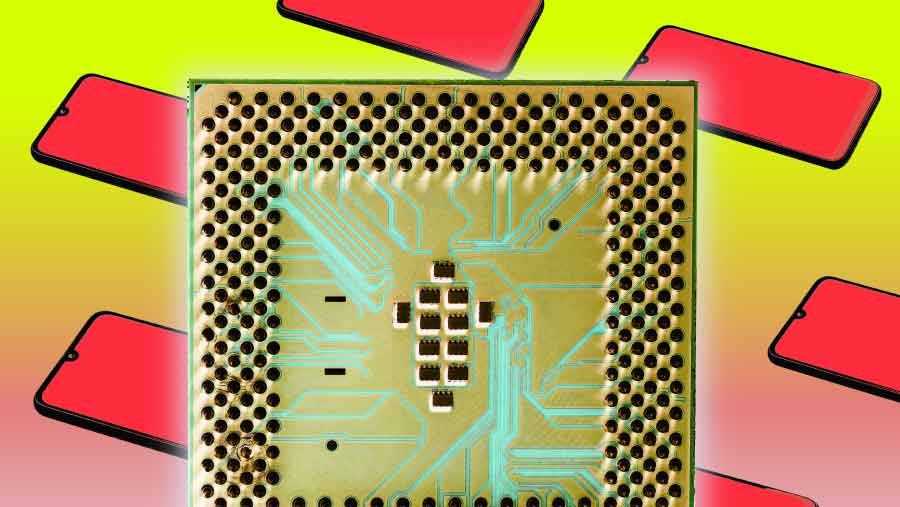Khudori juga mengkritik kecenderungan pemerintah memaksakan budidaya padi di wilayah yang secara ekologis tidak sesuai seperti di Papua Pegunungan. Menurutnya hal ini memakasa masyarakat yang secara ekologi dan secara lingkungan tak memungkinkan terpaksa menanam padi. Menurutnya, pemaksaan tersebut justru meningkatkan risiko ketahanan pangan nasional.
“Karena akan sangat berisiko ya kalau negeri seluas Indonesia yang sangat beragam, kepulauan, terus infrastruktur transportasinya juga, itu membuat kepastian pasokan ke wilayah-wilayah yang memang bukan produsen itu menjadi sangat berisiko.” kata Khudori.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga kini Jawa masih menyumbang sekitar 54–55% produksi beras nasional. Artinya jika terjadi goncangan besar di wilayah-wilayah produsen utama, terutama di Jawa, ketahanan pangan secara nasional akan terpengaruh.
Karena itu, ia menilai diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seharusnya menjadi pilar utama ketahanan pangan.
“Kalau yang didorong adalah bagaimana wilayah-wilayah yang memang secara ekologi itu bisa dikembangkan pangan-pangan lokal yang sangat berbeda, itu kita punya ketangguhan masing-masing.” katanya.
Risiko Jika Mengikat Pelaku Usaha Swasta
Khudori juga menyoroti potensi persoalan jika kebijakan satu harga dan satu kualitas dengan standar beras medium ini diberlakukan tidak hanya kepada Perum Bulog, tetapi juga pelaku usaha swasta.
“Kalau satu kualitas, satu harga, dan itu kualitasnya adalah medium, apakah ini juga mengikat publik, mengikat pelaku usaha swasta? Oke. Kalau ini mengikat pelaku swasta, menurut saya nggak tepat lah ya, nggak tepat.”
Ia menilai struktur industri penggilingan padi di Indonesia sangat beragam, baik dari sisi skala investasi maupun segmen konsumen yang dilayani. Menurutnya, investasi penggilingan padi skala kecil, penggilingan padi skala menengah, penggilingan padi skala besar adalah dua jenis investasi yang berbeda. Karena dua jenis investasi yang berbeda, produknya juga berbeda.
Lebih jauh, Khudori menegaskan bahwa beras Indonesia tidak lagi dapat diperlakukan sebagai komoditas tunggal.
“Beras itu bukan lagi komoditas yang tunggal. Ada penelitian Perhepi tahun 2016 yang menunjukkan itu, bahwa beras itu bukan lagi komoditas tunggal, tapi produk yang sangat beragam.”
Atribut kualitas seperti tekstur, warna, kadar patah, hingga aroma, menurutnya, merupakan nilai tambah yang memang ditawarkan produsen kepada konsumen. Karena itu, penyeragaman harga dan kualitas dinilai justru berseberangan dengan mekanisme pasar dan preferensi konsumen.
“Kalau pemerintah menyeragamkan ini tidak hanya buat Bulog, tapi juga oleh pelaku swasta, sebetulnya selain yang pertama tadi investasinya berbeda, produknya berbeda, yang kedua itu melawan pasar sebetulnya. Yang ketiga melawan preferensi konsumen. Tidak tepat.” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan beras satu harga akan dijual dengan harga yang sama di seluruh wilayah Tanah Air mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yakni di level Rp12.500/kg. Artinya, para pengecer bakal mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500/kg.
“Beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP bukan beras premium ya. Itu nanti keluar gudang kami rencanakan [seharga] Rp11.000. Di Sabang, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan sampai Papua. Tapi untuk harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi yaitu Rp12.500,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (12/1/2026).
Rizal menuturkan beras satu harga diterapkan karena harga beras di wilayah Indonesia bagian Timur bahkan tembus lebih dari Rp16.000/kg. Dengan aturan baru itu, nantinya seluruh wilayah dapat membeli beras seharga Rp12.500/kg.
(ell)