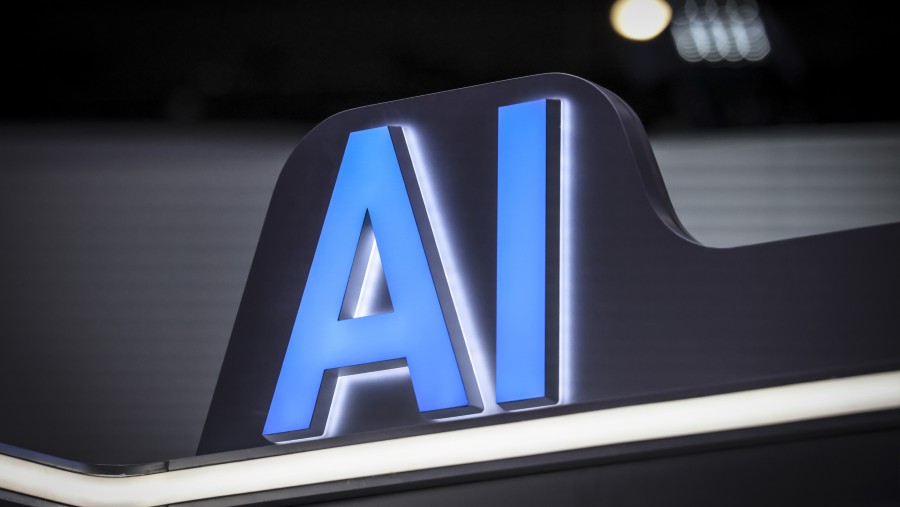Pada tahun 1990-an, kemunculan internet yang populer memicu optimisme bahwa sisi baik manusia akan mengalahkan keserakahan kapitalis. Kecenderungan alami kita untuk kebaikan, kerja sama, dan kreativitas, kata mereka, akan dimanfaatkan untuk merombak perdagangan dan budaya. Banyak dibicarakan tentang “kekuatan berbagi.” Seperti yang dikatakan Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web asal Inggris, “ide asli web adalah agar menjadi wahana kolaboratif.”
Itulah yang terjadi pada masa tersebut. Bahkan hingga pertengahan 2000-an, Clay Shirky dari NYU dalam bukunya Here Comes Everybody menegaskan bahwa “internet beroperasi atas dasar cinta.” Ide mulianya adalah bahwa semua orang termotivasi untuk berkontribusi dengan waktu dan bakat mereka secara online, bahkan ketika tidak ada janji keuntungan finansial secara langsung.
Namun, pada dekade 2010-an, platform besar mulai melakukan taruhan yang jauh lebih sinis terhadap dorongan-dorongan primitif manusia. Taruhan pertama dan paling terkenal adalah media sosial. Targetnya menjadi daya tarik adiktif dari lingkaran umpan balik dan emosi gelap seperti kemarahan dan kemarahan. Itulah cerita yang lebih dikenal. Namun, dengan melihat ke belakang, jelas bahwa banyak perusahaan ini melakukan taruhan yang jauh lebih besar pada aspek lain dari sifat manusia: kecintaan kita atas sebuah rasa nyaman.
Retensi pelanggan adalah prioritas di setiap industri, tetapi platform teknologi—yang nilainya bergantung pada efek jaringan yang semakin kuat seiring pertumbuhannya—menjadikannya ekstrem. Di kampus bisnis, mempertahankan pelanggan secara datar disebut sebagai menciptakan “biaya peralihan” atau, dengan lebih berwarna, “keterikatan konsumen.” Singkirkan hype tentang algoritma canggih, dan sebagian besar yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini hanya benar-benar penting jika membuat pengguna tidak berpaling.

Tujuan ini dengan baik diungkapkan oleh istilah dari budaya stoner: couchlock—ketidakmampuan untuk bergerak setelah merasa nyaman. Urban Dictionary mendefinisikannya sebagai “perasaan seolah-olah beratnya melebihi sejuta ton.” Platform-platform ini bertujuan untuk menciptakan versi digital dari perasaan tersebut: Jika mereka berhasil, membuka akun media sosial baru atau berbelanja di tempat lain selain Amazon terasa seperti tugas yang mustahil.
Secara strategis, upaya untuk mencapai “couchlock” telah mendorong platform-platform besar untuk membentuk diri mereka sendiri menjadi ekosistem yang komprehensif—di mana sebanyak mungkin kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan usaha minimal. Mereka bercita-cita menjadi segalanya, atau hampir segalanya, bagi semua orang, sepanjang waktu.
Google, yang awalnya merupakan mesin pencari, kini memproduksi ponsel, mengoperasikan YouTube dan layanan TV, serta terus memperluas jangkauannya. Apple Inc., yang awalnya merupakan perusahaan komputer, kini menjual perangkat wearable, layanan kesehatan, dan konten televisi.
Masih ada Amazon.com Inc. Perusahaan milik Jeff Bezos ini adalah yang paling ambisius: Mulanya adalah toko buku, untuk kemudian berubah wujud menjadi toserba, lalu menambahkan streaming video (2011), bahan makanan (2017), dan layanan kesehatan (2023).
Metafora lama tentang “walled garden” seolah usang, jadul, di era ketika perusahaan-perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan seutunya pada sekitar kehidupan kita.
Setelah kita terperangkap dalam “rumah yang nyaman”, peluang keuntungan mulai terlihat. Mengganti metafora, model platform memiliki kesamaan dengan kasino, dalam arti bahwa tidak peduli apa yang Anda lakukan di sana—platform selalu menang. Platform mengambil biaya, perhatian, data—semua dapat dipanen dari ratusan juta pengguna yang berkeliaran, serta penjual dan pengiklan yang menghuni platform tersebut.
Logika ini juga sebagian menjelaskan investasi besar-besaran yang dilakukan platform dalam bidang AI. Seperti teknologi baru lainnya, AI merupakan ancaman alami bagi bisnis-bisnis ini, yang teknologi dasarnya sudah berusia puluhan tahun.
Ada ancaman nyata bahwa pendatang baru seperti OpenAI dapat menantang Google Search atau Amazon Web Services dengan sukses. Namun, secara cerdik, platform-platform tersebut mungkin dapat menangkis tantangan AI dengan menggunakan AI sendiri demi memperkuat dominasi mereka, melindungi posisi monopoli, dan membenarkan investasi besar-besaran mereka.
Hal ini bergantung, lebih dari segalanya, pada penggunaan AI untuk semakin meningkatkan ketergantungan kita dan rasa ketergantungan yang sulit dilepaskan.
Ada dua cara yang mereka lakukan. Yang pertama adalah strategi lama dengan membuat segala sesuatunya lebih mudah: Memiliki pelayan otomatis untuk menangani tugas-tugas digital sangat menarik, dan segera mungkin terasa mustahil untuk melakukannya tanpa itu. Fakta bahwa orang menggunakan ChatGPT untuk “mensontek” hobi mereka sendiri menunjukkan betapa kita secara kompulsif mencari jalan yang mudah.
Yang lebih baru dan menarik adalah strategi penangkapan dimana hal tersebut bergantung pada membangun ketergantungan emosional. Perusahaan, tentu saja, telah lama berusaha membangun koneksi emosional dengan konsumen mereka. Pikirkan Marlboro, Coca-Cola, atau kultus modern Lululemon dan Apple. Seperti yang dijelaskan oleh ahli pemasaran Douglas Grisaffe dan Hieu Nguyen, tujuannya adalah membangun “pengaruh positif yang intens terhadap merek,” menciptakan “komitmen yang kuat untuk membeli kembali ... terlepas dari segala rintangan dan biaya.”
Namun, AI hari ini menambahkan dimensi baru. Film Her (2013) menggambarkan manusia yang jatuh cinta pada asisten digital mereka. Ketika OpenAI meluncurkan chatbot berbasis suara pada 2024, mereka memperingatkan bahwa “pengguna mungkin membentuk hubungan sosial dengan AI.” Hal itu tidak menghentikan perusahaan untuk memberikan suara pada chatbot-nya—“Sky”—yang terdengar sangat mirip dengan Samantha, karakter digital yang diperankan Scarlett Johansson dalam film ini.
Sebagai konsumen, sulit untuk amat kesal dengan produk yang memudahkan hidup. Ada sesuatu yang menarik dalam visi kehidupan di mana kita semua duduk layaknya bangsawan dengan robot yang melayani setiap kebutuhan kita. Namun, perkembangan semacam ini mungkin memiliki konsekuensinya sendiri, di mana setiap gelombang kemudahan juga melemahkan kemampuan kita untuk berfungsi tanpa perlengkapan teknologi kita.
Kelemahan kita sendiri menjadi ancaman yang nyata dan mendesak, meskipun kita mungkin menjadi terlalu nyaman untuk benar-benar peduli.
Anda mungkin pernah mendengar tentang “singularitas”—momen hipotetis ketika AI melampaui kecerdasan manusia. Pencapaiannya telah menjadi obsesi bagi banyak orang di dunia seputar kecerdasan buatan. Namun, terlepas dari apakah hari itu pernah tiba, model bisnis zaman kita memiliki jalannya sendiri. Mereka justru membawa kita menuju “sofalarity”: masa depan yang ditandai oleh ketiadaan total rasa tidak nyaman.
(bbn)