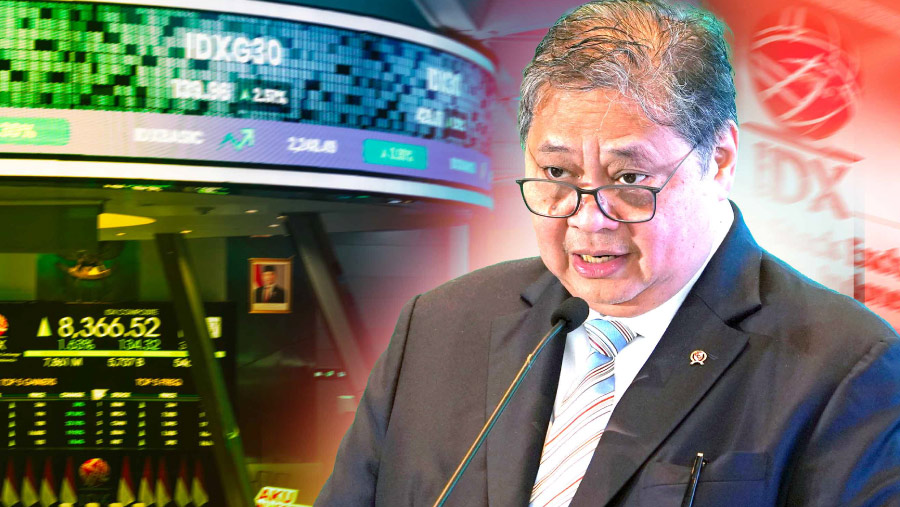Menurut Kartika, pendekatan teknis dari otoritas pasar modal Indonesia tak akan mampu mengubah keputusan MSCI.
“Analoginya seperti ini, kamu mau ekspor barang, pembeli sudah bilang tidak mau produk mengandung babi. Tapi kamu malah jelaskan bahwa babi itu sehat. Tidak akan diterima juga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy. Ia menyebut penghapusan FCA jauh lebih penting ketimbang sekadar mengejar free float minimum pasca-IPO untuk masuk indeks MSCI.

“MSCI tidak akan memasukkan semua emiten yang pernah mengalami FCA, UMA, suspensi, dan sanksi lainnya dalam setahun terakhir ke dalam indeksnya,” kata Budi pada Senin (19/5/2025).
Ia menyoroti khusus FCA Kriteria 10, yang mencakup saham-saham yang sebelumnya masuk dalam daftar UMA.
Budi menilai BEI seharusnya segera meninjau ulang atau menghapus aturan ini. Ia juga menilai langkah BEI menyurati MSCI untuk menjelaskan bahwa UMA bukan sanksi atau hukuman, dan bahwa FCA hanya meredam volatilitas harga selama tujuh hari, tidak cukup efektif.
Budi menilai sikap defensif semacam itu kurang tepat.
“BEI seharusnya mengevaluasi segala kebijakannya, bukan mereka [MSCI] yang harus memahami aturan-aturan BEI,” tegasnya.
Kartika juga menggarisbawahi dampak langsung FCA terhadap dinamika pasar. Volume transaksi, kata dia, langsung menyusut saat saham masuk dalam pengawasan FCA. Order book menjadi timpang, transaksi wajar di tengah nyaris tidak terjadi.
“Volume langsung hilang saat saham masuk FCA. Jadi, kamu tinggal lihat harga di bid-offer yang miring, jarang sekali ada transaksi wajar di tengah,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat saham menjadi tidak menarik bagi investor institusional global yang menuntut efisiensi harga dan transparansi. Kartika pun menilai penerapan FCA dan UMA belum konsisten.
Ia mempertanyakan mengapa saham-saham yang jatuh tajam tidak dikenai UMA, sementara saham-saham yang naik justru langsung disanksi.
“Kalau mau lindungi investor ritel, kenapa saham-saham yang harganya jatuh drastis tidak kena UMA? Unilever dari harga berapa jadi berapa, kenapa tidak dikenai UMA? Itu ada berapa investor ritel yang rugi?” ujar Kartika.
Ia menyarankan agar BEI mengevaluasi ulang pendekatan pengawasan pasar agar lebih selaras dengan praktik global.
Di luar negeri, kata Kartika, UMA hanya diterapkan dalam kasus berat seperti penipuan, litigasi hukum, atau pelanggaran serius lain. “Bukan karena sahamnya naik,” tegasnya.
Baik Kartika maupun Budi menilai, jika BEI ingin menjadikan pasar modal Indonesia lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing, maka reformasi regulasi menjadi langkah mendesak. Kebijakan yang melemahkan likuiditas seperti FCA harus dikaji ulang. BEI juga diminta lebih transparan, adil, dan objektif dalam membuat keputusan.
(dhf)