“Memang daya beli kita lemah, tapi kalau harganya semakin tinggi, ini maka dugaan saya masyarakat atau konsumen akan beralih ke alternatif produk yang lebih murah. Ini nanti tergantung naiknya akan seberapa besar, tapi saya rasa apakah ini akan memperparah daya beli, nggak juga,” tutur Riefky.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memprediksi sebaliknya dengan menyebut potensi iPhone bakal menjadi lebih murah ke depannya.
“Apakah dengan tarif 0% [iPhone] itu akan jadi lebih murah? Ya secara umum mestinya begitu karena ini berlaku umum berbagai jenis barang,” kata Faisal ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (22/7/2025).
Dia pun menilai ada kelemahan dari kebijakan tersebut yakni pemerintah belum memberikan penjelasan secara detil. Hal ini masih bergantung terhadap bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan penurunan tarif itu.
“Kalau bersandar kepada aturan umumnya, semuanya kena 0%, berarti kan termasuk di antaranya juga adalah impor untuk smartphone khususnya adalah iPhone,” ujar Faisal.
Sementara itu, jika iPhone yang berasal dari AS tetapi diproduksi di China, dia menekankan bahwa Indonesia mengimpor iPhone berupa produk jadi. Semisal produk itu didatangkan dari Negeri Tirai Bambu tersebut, maka secara neraca perdagangan, RI mengimpor dari Cina.
“Dan itu ter-capture dari peningkatan impor smartphone khususnya iPhone, dalam golongan smartphone, iPhone di dalamnya dari Cina semestinya bukan dari Amerika. Jadi artinya, pencatatan perdagangan barang begitu,” terang Faisal.
Akan tetapi, karena merk iPhone berasal dari AS, maka perdagangan jasanya dalam bentuk royalti dan lain-lain itu lari ke Negeri Paman Sam tersebut. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjual yakni dari Cina itu ada sebagian yang harus dibayarkan ke AS.
“Itulah dalam bentuk perdagangan jasanya karena pemilik merk adalah dari Amerika,” kata Faisal.
Daya Tawar Industri Berbasis Teknologi RI Masih Lemah
Riefky mengakui bahwa daya tawar industri atau manufaktur berbasis teknologi di Indonesia masih amat lemah. Indonesia masih jauh tertinggal dengan Vietnam dan Taiwan, bahkan di beberapa komponen masih ketinggalan dari Singapura atau Malaysia.
“Memang masih low value added [nilai tambah yang rendah] dan low technology [teknologi rendah]. Jadi memang posisi tawar kita tidak terlalu bagus di produk-produk manufaktur berbasis teknologi,” ujar Riefky.
Justru Indonesia jauh memiliki daya tawar tinggi pada produk-produk berbasis komoditas seperti kopi, minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan nikel, ucap Riefky. “Itu kita memiliki daya tawar tinggi, tapi selebihnya memang daya tawar kita masih relatif lemah.”
Dia menambahkan pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya saing serta menciptakan investasi berbasis teknologi ke Tanah Air. Hal in ibertujuan guna menguatkan daya tawar industri atau manufaktur berbasis teknologi domestik.
“Kita tahu banyak investasi yang nggak jadi masuk ke Indonesia, Apple, Microsoft, Tesla. Ini kan kita liat selama setahun belakang tuh banyak yang nggak jadi investasi ke Indonesia, malah di negara lain,” jelas dia.
Kemunduran ini terjadi karena iklim investasi dalam negeri tak kompetitif. Banyak praktik perburuan rente dan premanisme. Ini masih ditambah dengan kerumitan birokrasi dan administrasi. Belum cukup, masih ada persoalan dari sisi regulasi kompleks dan tumpang tindih.
“Ini membuat iklim investasi di Indonesia jadi nggak menarik,” terang Riefky.
Jika membandingkan dengan Malaysia dan Vietnam, para negara tetangga Indonesia ini telah memberikan kepastian terhadap investor. “Nah, hal-hal ini yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar investasi masuk termasuk investasi berbasis teknologi, sehingga kita memiliki daya saing yang kemudian kita memiliki posisi tawar lebih baik,” tegas dia.
“Ini memang kebijakan yang cukup struktural dan enggak bisa di-achieve (diraih) dalam waktu singkat. Jadi memang ini perlu reformasi yang cukup mendasar di iklim investasi kita,” pungkas dia.
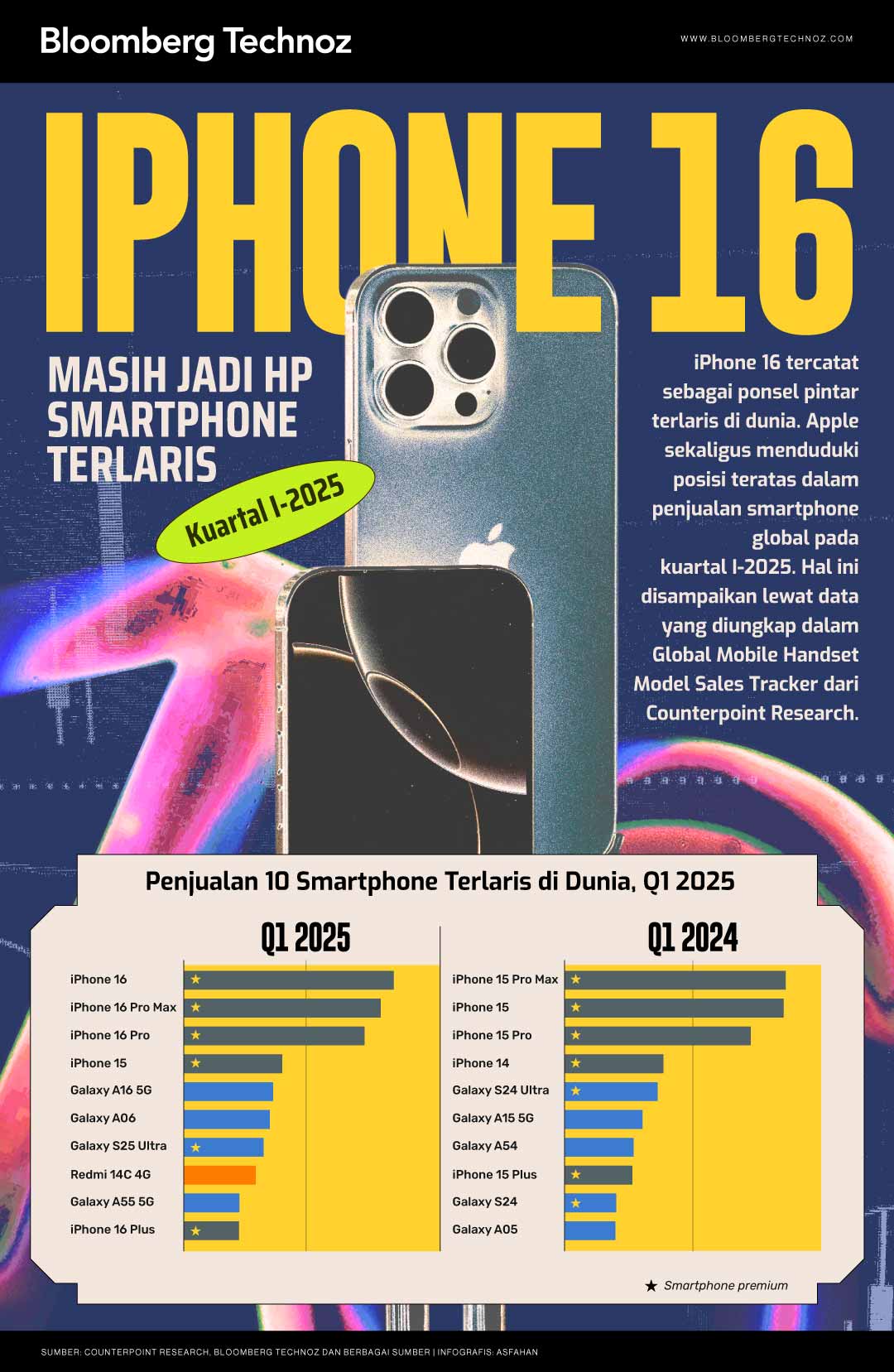
*) Artikel ini mendapat pembaruan lewat komentar dari ekonom CORE.
(wep)
































