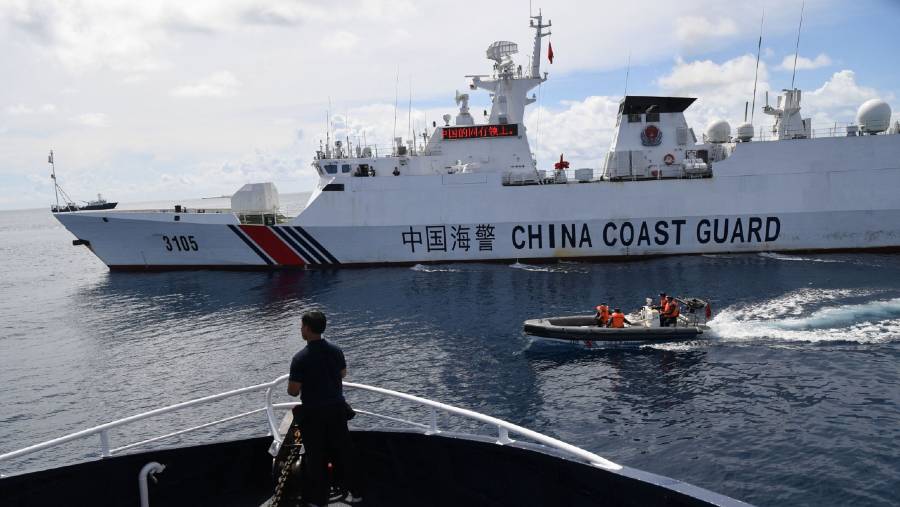Ekspor utama Indonesia ke AS saat ini antara lain tekstil, alas kaki, furnitur, produk perikanan, karet, kelapa sawit olahan, serta kabel dan komponen elektronik. Di semua lini ini, Indonesia menghadapi persaingan ketat dari Vietnam, Malaysia, India, Bangladesh, Thailand, hingga Filipina. Jika kualitas, kepastian suplai, dan biaya pengiriman tak ditingkatkan, importir AS bisa tetap beralih ke negara pesaing meski tarif mereka lebih tinggi.
Sebagai bagian dari upaya diplomasi dagang yang lebih luas, Indonesia juga menyepakati komitmen pembelian energi dan pertanian dari AS senilai hampir USD20 miliar. Rinciannya, USD15 miliar untuk energi seperti LNG, batubara, dan minyak, serta USD4,5 miliar untuk produk pertanian seperti kedelai, gandum, daging, dan jagung.
Membebani Neraca Dagang
Riset Kiwoom menilai kesepakatan ini berpotensi membebani neraca perdagangan Indonesia dalam jangka pendek dan menekan nilai tukar rupiah jika arus ekspor dan investasi tidak ikut mengimbangi.
“Risiko terbesar adalah jika realisasi impor berlangsung cepat, tapi peningkatan ekspor akibat tarif 19% justru lambat. Efeknya bisa negatif untuk rupiah,” tulis laporan itu. Belum lagi, langkah ini berpotensi bertabrakan dengan agenda swasembada pangan nasional.
Salah satu komponen dalam diplomasi dagang ini adalah rencana pembelian 50–70 unit pesawat Boeing oleh maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dan Batik Air. Nilai kesepakatan ini diperkirakan mencapai USD10–11 miliar. Namun, Kiwoom menyoroti sejumlah hal krusial: siapa yang akan membayar transaksi jumbo ini?

Saat ini, Garuda tengah mendapat sokongan dari Danantara Indonesia senilai USD405 juta dalam bentuk shareholder loan, yang disebut bisa naik hingga USD1 miliar. Namun, pertanyaan muncul apakah pembelian Boeing ini akan dibebankan ke APBN, mengingat Danantara disebut tidak wajib melapor ke DPR.
Kiwoom mencatat bahwa pembelian pesawat dalam jumlah besar ini bisa mendorong ekspansi rute internasional dan menumbuhkan sektor pendukung seperti MRO (Maintenance, Repair & Overhaul). Namun, juga ada risiko keuangan, terutama bagi Garuda yang baru mulai pulih dari krisis.
“Kalau pembeliannya didasarkan pada kebutuhan dagang dan bukan analisis bisnis murni, risikonya besar. Potensi overcapacity tinggi, terutama kalau traffic penumpang tidak naik signifikan,” tulis laporan tersebut.
Sejauh ini, pasar belum menunjukkan reaksi negatif karena Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan hingga Mei 2025 sebesar USD15,38 miliar.
Surplus ini sudah berlangsung 61 bulan berturut-turut. Namun, investor akan mencermati apakah rencana impor besar dari AS akan terealisasi dalam waktu dekat dan apakah ekspor benar-benar bisa terdorong oleh penurunan tarif.
Jadi, meskipun tarif 19% dari AS memang lebih rendah dibandingkan tarif negara pesaing, tapi Indonesia tidak bisa berpuas diri. Tanpa pembenahan rantai pasok, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas produk, peluang untuk memperluas ekspor tetap bisa lepas.
Lebih jauh, rencana pembelian pesawat dan impor besar-besaran dari AS bisa menjadi beban jika tidak ditopang pertumbuhan ekspor yang sehat.
(dhf)