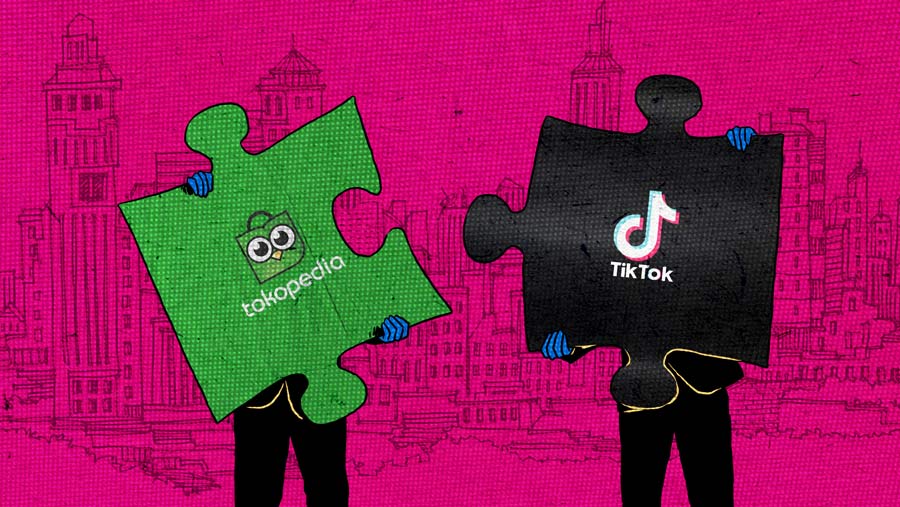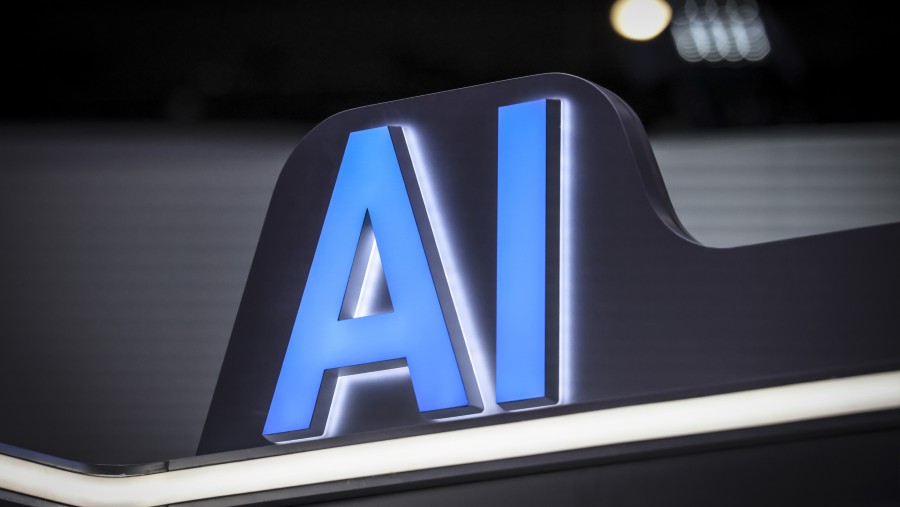Antara Mimpi Hijau dan Bayang-bayang Nuklir
Yohannes Krishna Fajar Nugroho Narastradi
21 November 2025 17:39

|
Penulis: Yohannes Krishna Fajar Nugroho Yohannes Krishna Fajar Nugroho, M.I.Kom. adalah seorang advisor di Blocksphere.id dengan latar belakang pendidikan Magister Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Ia memiliki pengalaman profesional di bidang jurnalistik dan teknis, terutama dalam instalasi dan pengelolaan sistem radar kelautan di wilayah Sulawesi dan Papua. Dalam bidang akademik, Fajar dikenal sebagai satu-satunya mahasiswa pascasarjana di IISIP Jakarta yang secara khusus meneliti isu deradikalisasi dan terorisme dalam perspektif komunikasi. Fokus keilmuannya mencakup komunikasi strategis, literasi media, dan studi keamanan non-militer. |
Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan akan energi fosil dan emisi tinggi. Sekitar 66% listrik Indonesia masih berasal dari batubara dengan kontribusi pada sektor energi menyumbang sekitar 650 juta ton karbon dioksida pada 2022. Energi bersih yang bersifat renewable hanya mencakup sekitar 13-15% dari total kapasitas listrik. Padahal, pemerintah menargetkan 23% pada 2025. Namun realisasi di lapangan masih jauh di bawah harapan, sementara investasi yang masuk ke sektor ini hanya sekitar US$1.5 miliar tahun lalu, sangat jauh dari kebutuhan estimasi US$150 miliar.

Dengan kesenjangan sebesar ini, apakah Indonesia mampu hanya mengandalkan energi terbarukan? Atau saatnya Indonesia memilih opsi yang kontroversial dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)?
Faktanya, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang ketenaghanukliran. UU Nomor 10/1997 tentang ketenaganukliran yang dibuat untuk memastikan bahwa pemanfaatan energi nuklir di Indonesia hanya digunakan untuk tujuan damai, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan energi nasional, serta dilakukan dengan keamanan dan keselamatan yang ketat. Undang-undang ini mendiferensiasi dua fungsi besar Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai pihak yang menggawangi penggunaan tenaga nuklir, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai pihak yang mengawasi penggunaan nuklir. Pemisahan ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengikuti standard International Atomic Energy Agency (IAEA).
Baca Juga
Wacana penggunaan PLTN bukan merupakan hal baru. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto, mantan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), menuturkan bahwa wacana pembangunan PLTN sudah ada sejak jaman Presiden Soeharto. “Namun karena waktu itu ada kasus di Chernobyl, pembangunan PLTN jadi tertunda-tunda.”Hal ini menjadi salah satu dari sekian banyak barriers yang perlu dilalui oleh pemangku kepentingan yang ada.
Pada 2060 mendatang, Indonesia menargetkan sebanyak 73,6% pasokan listrik berasal dari energi bersih. Dalam mengimplementasikan hal itu, rencana transisi mencakup penghentian bertahap pembangkit fosil dan percepatan PLTS dan PLTA. Tapi hingga saat ini nuklir masih dianggap yang paling sangkil dan mangkus dalam kategori baseload low-carbon karena mampu mengisi celah ketika energi surya dan angin bersifat labil dan tidak dapat berfungsi sebagai sumber energi dasar.
Namun, diskursus tentang PLTN di Indonesia tidak sesederhana menyalakan saklar. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam implementasi pembangunan PLTN. Selain biaya awal yang tinggi dan isu teknologi, tantangan terbesar justru terletak pada persepsi publik dan regulasi, serta kondisi geopolitik regional dan global. Selama puluhan tahun, kata “nuklir” kerap diasosiasikan dengan bencana Chernobyl dan Fukushima yang memicu ketakutan akan keselamatan dan limbah radioaktif.
Padahal, perkembangan teknologi reaktor generasi baru jauh lebih aman, sangkil, dan ramah lingkungan dibandingkan pada dekade 1980-an. Jika Indonesia benar-benar ingin mengejar target emisi rendah dan kemandirian energi, debat soal PLTN harus melampaui stigma masa lalu dengan mengedepankan kajian ilmiah, transparansi risiko, dan partisipasi publik yang bermakna.
Nuklir untuk energi dan senjata: Dua jalur yang berbeda arah
Penting bagi kita membedakan antara nuklir untuk energi dan nuklir untuk senjata. “Ketika kita berbicara soal nuklir, orang banyak akan beranggapan bahwa itu adalah senjata berbahaya,” Djarot memaparkan. "Keduanya memang bersumber dari prinsip yang sama, yaitu reaksi fusi inti atom tetapi arah dan tujuannya sangat berbeda."
Dalam konteks energi, reaksi fusi dilakukan secara terkendali di dalam reaktor untuk menghasilkan panas yang diubah menjadi listrik. Sementara pada senjata nuklir, reaksi fusi terjadi secara tak terkendali dan eksplosif, menghasilkan daya ledak yang luar biasa besar.
Kesalahpahaman ini yang menjadi momok di kalangan publik. Padahal, secara hukum dan politik, Indonesia telah menegaskan posisinya dengan sangat jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 10/1997 tentang Ketenaganukliran, Indonesia hanya menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Komitmen itu juga diperkuat dengan ratifikasi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengembangkan senjata nuklir dalam bentuk apa pun.
Di tingkat internasional, IAEA memiliki mekanisme pengawasan sangat ketat terhadap setiap aktifitas nuklir, termasuk di Indonesia. Setiap pengembangan, riset, hingga pengadaan bahan bakar nuklir harus mendapat verifikasi dan persetujuan dari IAEA dan BAPETEN sebagai pengawas nasional. Artinya, tidak ada ruang abu-abu antara “nuklir untuk energi” dan “nuklir untuk senjata”— selama sistem pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia merupakan contoh konkret bagaimana mengoptimalisasi nuklir tanpa menimbulkan ancaman militer. Ketiganya berhasil membangun infrastruktur PLTN dengan tingkat keselamatan tinggi, efisiensi energi yang stabil, dan regulasi publik yang transparan. Indonesia seharusnya dapat belajar dari mereka: bahwa energi nuklir tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya, melainkan sebagai teknologi yang menuntut tata kelola yang baik dan disiplin yang matang.
Tentu saja, semua itu tak lepas dari evolusi teknologi nuklir itu sendiri. Dari reaktor generasi awal yang besar dan kompleks, kini dunia tengah menyongsong era reaktor generasi ke empat yang jauh lebih aman, modular, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Teknologi Reaktor Nuklir Generasi ke-4
Jika di masa lalu energi nuklir diwarnai oleh kekhawatiran dan kecelakaan, di masa depan itu justru diwarnai oleh inovasi dan efisiensi. Dunia kini bergerak menuju reaktor generasi keempat (Gen-IV), yaitu sebuah lompatan teknologi yang berfokus pada keamanan intrinsik, efisiensi bahan bakar, dan minimalisasi limbah radioaktif.
Teknologi Gen-IV dirancang dengan konsep _fail-safe_, yang mana sistemnya dapat menghentikan reaksi secara otomatis tanpa intervensi manusia ketika terjadi gangguan. Beberapa desain bahkan menggunakan pendingin cair logam (seperti natrium atau timbal) atau gas helium bertekanan, yang membuat risiko kebocoran thermal jauh lebih kecil dibandingkan sistem berbasis air pada reaktor konvensional. Haendra Subekti, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (BAPETEN), menambahkan bahwa teknologi Gen-IV dapat memastikan nuklir benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai energi. “Paling tidak, nuklir ini tidak dapat diubah sebagai senjata” ujarnya.
Selain itu, Gen-IV memungkinkan pemanfaatan bahan bakar uranium dan thorium secara lebih sangkil, bahkan sebagian desainnya mampu mengolah kembali limbah radioaktif menjadi bahan bakar baru, sehingga residu yang tersisa jauh lebih sedikit dan lebih mudah dikelola. Hal ini menjawab salah satu ketakutan publik terbesar: persoalan limbah nuklir yang dianggap abadi.
Dari sisi efisiensi, reaktor generasi keempat juga menjanjikan kapasitas daya lebih besar dengan ukuran lebih kecil, terutama dalam bentuk Small Modular Reactor (SMR) yang memungkinkan pembangunan reaktor secara modular. Ia dapat dipasang di wilayah terpencil, dan disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal — tanpa memerlukan infrastruktur raksasa seperti PLTN konvensional. Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok kini berlomba mengembangkan prototipe SMR komersial.
Menariknya, Indonesia pernah melirik ke arah ini. Pada 2023, BATAN dan BAPETEN bersama IAEA telah melakukan studi kelayakan terhadap penerapan SMR di Kalimantan dan Bangka Belitung. Kajian ini masih bersifat awal, tetapi menandakan adanya keseriusan pemerintah dalam melihat potensi nuklir baru yang lebih aman dan realistis.
Bagi Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan wilayah dengan kebutuhan energi berbeda-beda, SMR dapat menjadi solusi transisi yang strategis. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan listrik di daerah terpencil, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem energi yang tangguh dan adaptif. Pandu Sastrowardoyo, host podcast Bloomberg Technoz, berpendapat bahwa Small Modular Reactor (SMR) ideal untuk digunakan di Indonesia. Namun, satu hal yang tak boleh dilupakan: teknologi secanggih apa pun akan sia-sia tanpa tata kelola politik dan kebijakan yang kuat. Karena itulah, diskursus mengenai energi nuklir tak dapat lepas dari konteks geopolitik global dan regional di mana energi sering kali menjadi alat pengaruh dan penentu arah kebijakan nasional.
Geopolitik Energi: Antara Tekanan Global dan Kemandirian Nasional
Dalam konteks global, energi bukan hanya urusan ekonomi. Lebih dari itu, ia sudah menjadi alat diplomasi dan hegemoni. Negara yang mampu menguasai sumber energi strategis secara otomatis memegang posisi tawar yang tinggi dalam percaturan geopolitik dunia. Dari situ, keputusan Indonesia untuk melirik nuklir akan selalu berada dalam bayang-bayang kepentingan global.
Sejarah menunjukkan, setiap negara berkembang yang berupaya membangun teknologi nuklir akan selalu berada di bawah sorotan ketat. Bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga kekhawatiran terselubung tentang potensi proliferasi, yakni kemungkinan teknologi sipil dialihkan menjadi militer. Negara-negara maju, terutama yang memiliki pengaruh besar di IAEA seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, cenderung bersikap ambivalen: di satu sisi mendukung transisi energi bersih, tetapi di sisi lain juga membatasi akses teknologi nuklir dengan alasan keamanan global.
Kondisi ini menciptakan paradoks bagi negara seperti Indonesia. Di satu sisi kita didorong untuk menekan emisi dan mempercepat transisi energi hijau, di sisi lain setiap langkah menuju nuklir perlu mendapat clearance dari mekanisme internasional seperti IAEA dan Non-Proliferation Treaty (NPT). Artinya, kedaulatan energi kita masih sebagian tergantung pada “izin global”.
Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia berpotensi menjadi pionir nuklir sipil. Negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam masih dalam tahap riset dan regulasi. Namun, menjadi pionir berarti juga memikul risiko geopolitik: tekanan diplomatik, pengawasan teknologi, bahkan persaingan pengaruh dari kekuatan besar yang memperebutkan pasar energi regional.
Persaingan ini bukan sekedar bisnis energi, melainkan bagian dari strategi hegemoni global, di mana teknologi, investasi, dan regulasi energi digunakan sebagai soft power dan alat diplomasi sehingga dapat membentuk suatu Technological Dependency untuk memperluas pengaruh politik. Tidak berlebihan bila dikatakan energi nuklir dapat menjadi “senjata politik baru” dalam menentukan posisi Indonesia di peta dunia.
Karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang cermat dari pemerintah dan lembaga terkait. Isu nuklir bukan sekadar urusan teknis dan lingkungan, tetapi juga narasi kedaulatan. Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa pembangunan PLTN bukan bentuk ketergantungan baru pada teknologi asing, melainkan langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Dengan pendekatan ini, setiap kerja sama—baik dengan Rusia (melalui Rosatom), Amerika Serikat (melalui Westinghouse), atau Tiongkok (melalui CNNC)—harus ditempatkan dalam kerangka equal partnership, bukan subordinasi.
Dr. Ir. Arnold Sutrisnanto, selaku Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia, menegaskan bahwa secara teknis dan regulasi Indonesia sudah mampu untuk memiliki PLTN. “Kita sudah punya reaktor nuklir, dan mengoperasikannya. Tidak ada kecelakaan, tidak ada radiasi yang bocor” ujarnya. Lebih lanjut, Arnold menekankan bahwa untuk keluar dari tekanan status quo, perlu kehendak yang kuat dari presiden Indonesia.
Dengan kata lain, pembahasan mengenai nuklir bukan hanya soal teknologi dan ekonomi, lebih dalam lagi hal ini adalah arena pertarungan kedaulatan. Akan timbul satu pertanyaan sederhana: apakah Indonesia mampu berdiri sebagai negara independen yang menentukan arah energi masa depannya sendiri, atau tetap berada dalam bayang-bayang persetujuan elit global yang mengendalikan akses teknologi nuklir sebagai instrumen kontrol geopolitik?
Realita bahwa Indonesia masih harus menunggu lampu hijau dari mekanisme internasional untuk sekadar menggunakan nuklir sebagai energi menunjukkan bahwa kemerdekaan kita masih belum sepenuhnya paripurna. Pada akhirnya, kami sampai pada kesimpulan bahwa selama energi bangsa ini masih tergantung pada restu pihak asing, maka perayaan kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun hanya sebatas seremonial belaka: arena kedaulatan belum benar-benar hadir sebagai realitas kekuasaan negara. Dalam dunia modern, penguasaan energi adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan negara, dan negara yang bergantung pada persetujuan asing untuk mengakses energinya sendiri, pada dasarnya, sedang menyerahkan masa depannya kepada kepentingan geopolitik pihak lain.
DISCLAIMER
Opini yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap, kebijakan, atau pandangan resmi dari Bloomberg Technoz. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau validitas informasi yang disajikan dalam opini ini.
Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan verifikasi dan mempertimbangkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan berdasarkan opini yang disampaikan. Jika terdapat keberatan atau klarifikasi terkait isi opini ini, silakan hubungi redaksi melalui contact@bloombergtechnoz.com
Tentang Z-ZoneZ-Zone merupakan kanal opini di Bloomberg Technoz yang menghadirkan beragam pandangan dari publik, akademisi, praktisi, hingga profesional lintas sektor. Di sini, penulis bisa berbagi ide, analisis, dan perspektif unikmu terhadap isu ekonomi, bisnis, teknologi, dan sosial. Punya opini menarik? |
(yhn)