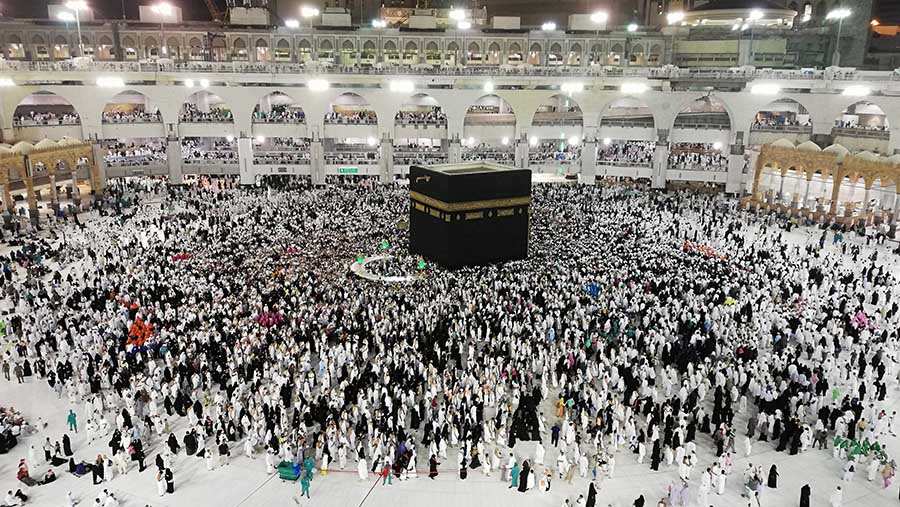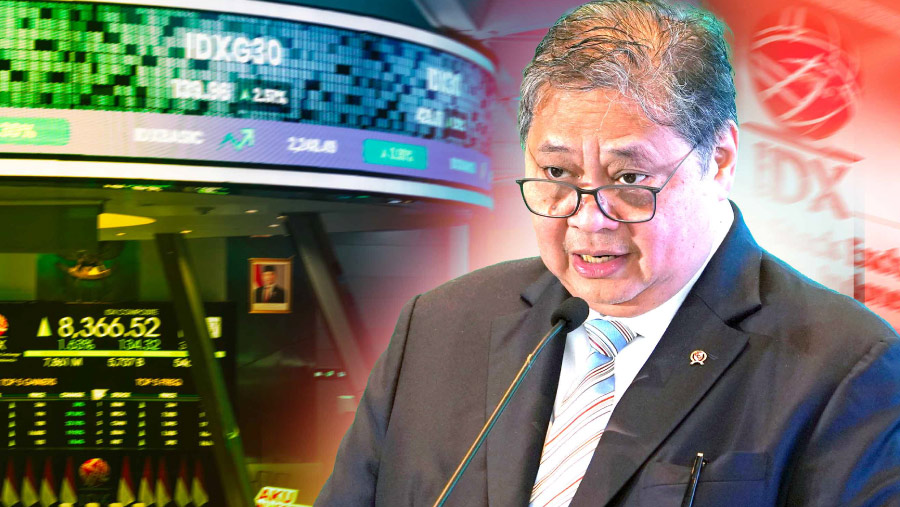Pertama, empty nest syndrome, yaitu kondisi ketika anak-anak sudah dewasa dan meninggalkan rumah, membuat pasangan menyadari bahwa kedekatan emosional mereka telah lama pudar.
“Selama bertahun-tahun, fokus mereka pada anak, bukan pada hubungan. Begitu anak pergi, mereka berhadapan dengan ruang kosong, baik secara emosional maupun fisik,” jelasnya.
Kedua, masalah finansial sering kali menjadi sumber konflik baru di usia senja. Transisi menuju masa pensiun, perubahan penghasilan, hingga perbedaan cara pandang dalam mengelola uang dapat memperparah ketegangan yang sudah ada.
“Menariknya, beberapa studi menemukan bahwa pria yang sudah mapan secara finansial justru lebih berani mengambil keputusan untuk bercerai karena merasa lebih bebas memulai hidup baru,” ujar Putri.
Ketiga, perubahan harapan dan nilai hidup juga menjadi faktor penting. Di usia paruh baya, banyak individu mulai merenungkan makna kebahagiaan dan kebermaknaan diri.
“Fase ini sering disebut midlife transition, di mana kebutuhan untuk aktualisasi diri semakin kuat. Jika pernikahan tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi, perceraian bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan emosional,” ungkapnya.
Keempat, perubahan sosial turut berperan besar. Norma masyarakat kini lebih terbuka terhadap perceraian, sehingga pasangan lanjut usia tidak lagi merasa harus mempertahankan hubungan demi pandangan publik.
“Mereka ingin bahagia dengan cara yang lebih autentik dan sehat, tanpa merasa bersalah,” tambah Putri.
Meski demikian, Putri mengingatkan bahwa perceraian di usia lanjut tetap memiliki dampak psikologis yang mendalam.
“Bisa muncul perasaan kehilangan identitas, penurunan harga diri, dan kekhawatiran tentang masa depan. Tapi di sisi lain, bagi sebagian orang, perceraian justru menjadi awal baru untuk menyusun ulang hidup,” katanya.
Menurutnya, keputusan untuk berpisah di usia senja seharusnya tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan hasil dari proses refleksi panjang dan kebutuhan untuk menjadi manusia yang utuh.
“Masyarakat perlu berhenti menempelkan stigma. Setiap keputusan, baik untuk bertahan maupun berpisah, adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan diri,” tegas Putri Langka.
Senada dengan itu, Seksolog Zoya Amirin menjelaskan bahwa gray divorce tidak hanya ditentukan oleh usia individu, melainkan juga oleh lamanya perjalanan bersama.
“Kalau seseorang berusia 52 tahun tapi baru menikah 1–3 tahun, itu tidak termasuk gray divorce. Istilah ini berlaku bagi pasangan yang menua bersama cukup lama, lalu memutuskan berpisah,” ujarnya.
Zoya menambahkan, fenomena ini bukan semata karena ego yang menurun, melainkan juga karena kelelahan emosional setelah bertahun-tahun beradaptasi.
“Bisa jadi mereka merasa anak-anak sudah besar, mampu mandiri, dan tidak perlu lagi mempertahankan peran sebagai pasangan, cukup sebagai orang tua,” jelasnya.
Menurut Zoya, dalam banyak kasus, gray divorce adalah bentuk “never ending adjustment”, yaitu upaya panjang untuk tetap saling menghargai meski cinta berubah bentuk.
“Masih ada kasih sayang, tapi juga kesadaran bahwa kebersamaan tidak harus memenjarakan. Ada saatnya perpisahan justru menjadi wujud penghormatan terhadap diri sendiri dan pasangan,” pungkasnya.
(dec/spt)