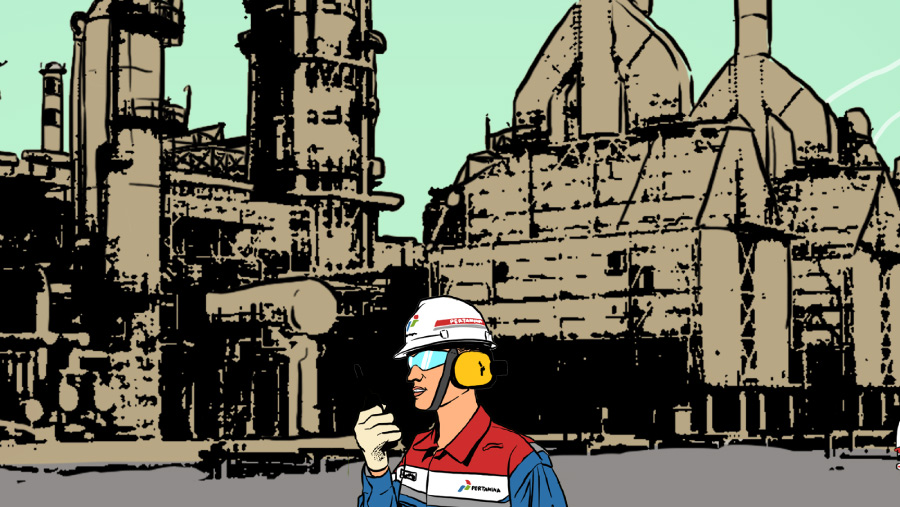Piyu menyoroti Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 yang mengatur pungutan 2% dari tiket konser, dibayarkan setelah acara berlangsung. Skema itu dinilai tidak masuk akal karena pencipta lagu ikut menanggung risiko bersama promotor.
“Sound engineer, vendor, hotel, semua sudah dibayar sebelum panggung dimulai. Tapi pencipta lagu baru menerima hak setelah konser, bahkan seringkali berdasarkan perkiraan, bukan log data pemakaian lagu. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
AKSI mendorong agar lisensi musik wajib diselesaikan sebelum pertunjukan berlangsung, sebagaimana praktik internasional. Menurut Piyu, mekanisme itu akan memberi kepastian hukum, sekaligus membantu promotor mengajukan anggaran transparan ke sponsor.
“Kalau lisensi beres sebelum acara, penyelenggara bisa menghitung margin dengan jelas. Justru ini lebih fair, kenapa malah ditentang?” katanya.
Kontroversi makin melebar setelah sempat muncul klaim bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya termasuk dalam daftar pungutan royalti. Padahal, Pasal 43 UU Hak Cipta tegas melarang penarikan royalti atas lagu nasional. “Restoran, hotel, kafe sampai Indonesia Raya pun mau ditarik royalti. Ini absurd,” tegas Piyu.
Dari sisi LMK, WAMI berdalih bahwa sistem pemungutan kolektif merupakan praktik global yang sudah berjalan lebih dari seabad. WAMI, yang tergabung dalam federasi internasional, menilai Indonesia tidak bisa menutup diri dari standar global.
“Lagu Indonesia juga diputar di luar negeri. Royalti tidak bisa hanya dibatasi pada artis yang terdaftar, karena extended collective license memberi kewenangan untuk menarik secara menyeluruh,” ujar perwakilan WAMI.
Meski begitu, musisi menilai dalih “standar internasional” tidak bisa menjadi pembenaran atas mekanisme yang mengebiri hak pencipta di dalam negeri. “Ini sudah era digital, semua bisa dicatat. Kenapa pungutannya masih pakai sistem blanket yang serba kira-kira?” tutup Piyu.
(fik/spt)