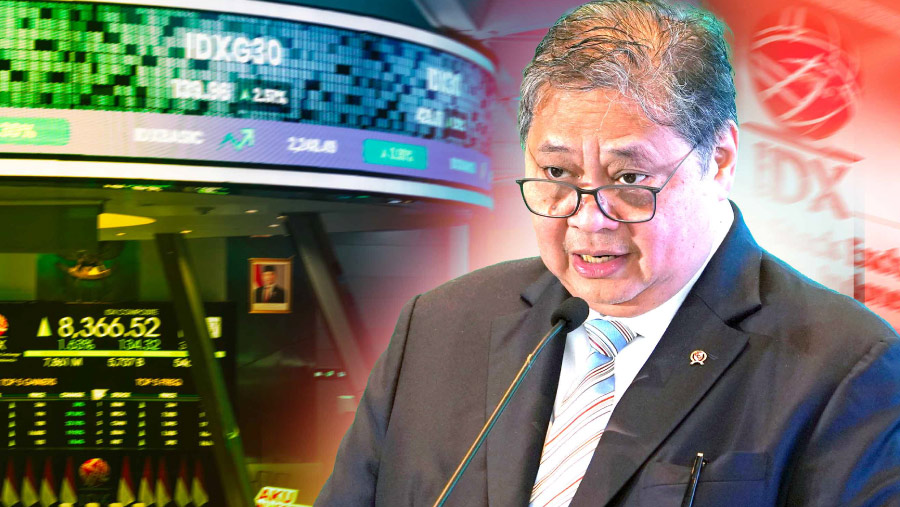Sementara itu, untuk DME subsidi dibutuhkan sebesar Rp34.069 per 3 kg. Dalam setahun, estimasi kebutuhan DME sebesar 10,78 juta ton/tahun atau setara Rp123 triliun per tahun.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp41 triliun yang merupakan risiko kenaikan subsidi.
“Tantangan keekonomian di mana estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Dan juga analisis perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” kata Arsal dalam rapat bersama Komisi XII dikutip Selasa (6/5/2025).
Arsal memang berkali-kali menyebut harga keekonomian DME tak ekonomis dibandingkan dengan harga LPG. Bahkan, ketika pemerintah menginginkan hilirisasi batu bara menjadi DME tetap dijalankan, PTBA menyebut masih membutuhkan kajian yang mendalam.
“DME memang kita perlu dilakukan kajian yang sangat mendalam ya karena disamping investasinya besar, ya itu juga harus benar-benar memberikan nilai tambah buat bangsa dan negara ini,” ujarnya.
“Jangan sampai nanti kita ujug-ujug antara cost sama yang dibandingkan dengan subsidi ini, kan kita harapkan ini biayanya ini kalau ini nanti lebih murah tentunya kita jalan gitu kan.”
Porsi Biaya
Di sisi lain, Arsal mengelaborasi estimasi biaya proyek DME paling tinggi berada di tingkat antara (midstream) hingga hilir (downstream) mendapatkan porsi sebesar 85%. Sementara itu, biaya hulu (upstream) atau yang ditangani PTBA hanya mendapat porsi 15%—16% untuk urusan harga batu bara.
Berdasarkan paparan PTBA, biaya upstream sebesar US$145/ton DME, sedangkan biaya midstream mencapai US$412—US$488/ton DME atau mendapat porsi sekitar 45%—49%.
Biaya estimasi downstream sebesar US$62/ton DME yang mendapat porsi 6%—7%. Adapun, biaya distribusi sebesar US$292/ton DME atau sebesar 30%—32%.
Dengan demikian, harga DME yang dihasilkan sebesar US$911/ton—US$987/ton DME.

Cari Investor
Arsal mengungkapkan PTBA hingga saat ini masih berdiskusi untuk mencari investor yang bisa menghasilkan teknologi dengan lebih murah.
“Kalau ada yang lebih murah, kami prinsipnya setuju. Untuk itu kami memang lagi bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Siapa nih investornya yang dahulu ada Air Products, membawa teknologi, bawa duit. Cuma kan mahal kan ya,” ucapnya.
“Nah, ada enggak yang dapat lagi yang seperti itu [Air Products], tetapi teknologinya bagus, harganya bisa lebih murah. Paling tidak, misalnya tidak ada subsidinya, ini masih bisa jalan. Paling tidak, enggak ada duit yang kita beli LPG, tetapi khusus digunakan untuk di Indonesia. Minimum kita mempunyai added value di tenaga kerja, pajak yang ada di dalam. Itu juga kita setuju.”
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pernah mengatakan dalam perkembangan proyek hilirisasi batu bara khususnya DME diperlukan adanya komitmen awal yang kuat, sehingga tidak terulang kegagalan seperti kerja sama PTBA dengan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemicals, Inc (APCI).
“Kami memastikan di awal. Jadi, kalau Air Products kemarin itu kan juga agak lama karena mereka minta ada jaminan penjualan pasokan. Pada saat mereka minta keputusan, kita agak terlambat. Jadi, kita tidak mau kehilangan momen,” kata Yuliot ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).
Ide gasifikasi batu bara menjadi DME pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah dipasrahkan pemerintah ke Bukit Asam, dengan bantuan investasi dari APCI asal AS.
Proyek itu sejatinya direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.
Dengan mendatangkan investasi asing dari APCI, proyek itu mulanya digadang-gadang sanggup menghasilkan DME sekitar 1,4 juta ton per tahun dengan memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun.
Namun, pada medio 2023, APCI hengkang dari proyek tersebut untuk fokus menggarap proyek hidrogen biru di AS. Keputusan hengkang tersebut lantas membuat kelanjutan nasib proyek gasifikasi batu bara menjadi DME terkatung-katung hingga saat ini.
(mfd/wdh)