Fabby juga menganalogikan seseorang ingin membeli rumah, tetapi tidak memiliki biaya untuk membayar uang muka. Namun, orang tersebut memiliki aset sebuah mobil dengan usia pakai yang cukup lama. Daripada mempertahankan mobil dan meminjam uang di bank untuk membayar uang muka, dia menyarankan agar orang itu menjual mobilnya.
“Ketimbang kita pinjam duit buat DP [down payment] rumah tadi, padahal kita punya aset yang mungkin dalam berapa waktu ke depan enggak lagi menarik. Kenapa? Ya kalau kayak mobil itu sederhana saja, kan banyak online transport dan kalau dihitung-hitung mungkin lebih murah daripada mobil sendiri,” ucapnya.
Biaya Produksi Listrik
Menurut Fabby, pemerintah maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tidak pernah menghitung dampak jangka panjang pensiun dini PLTU untuk digantikan dengan EBT. Menambah bauran EBT padahal dinilainya lebih cepat untuk menggantikan PLTU yang telah dipangkas dapat mendatangkan investasi.
“Kalau pemerintah menggunakan APBN untuk memensiundinilkan PLTU milik PLN, itu sebenarnya menguntungkan buat pemerintah dalam arti dampaknya dalam jangka menengah itu biaya produksi tenaga listrik turun, subsidi turun,” ujarnya.
“Jadi kita bilang pakai aset PLN untuk investasi energi terbarukan. Selama ini kan PLN mengalami kesulitan. Kalau dia mau investasi ke energi terbarukan, enggak ada duitnya. Nah sekarang asetnya itu.”
Di sisi lain, energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, hidro, tidak memiliki ongkos penambangan sehingga biaya penyediaan tenaga listrik akan lebih terkendali.
Berdasarkan perhitungan IESR, dengan meningkatkan bauran EBT di atas 30% pada 2030, biaya produksi tenaga listrik bisa turun hingga 10%. Jika biaya operasional berkurang karena PLTU juga berkurang, tetapi EBT bertambah, maka biaya penyediaannya juga berkurang.
“Jadi seharusnya pemerintah melihat itu, karena ke depan beban subsidi untuk listrik PLN itu akan menurun justru,” tutur Fabby.
Dia menyebut ketika pemerintah telah memadamkan PLTU, emisi karbon berkurang. Avoided carbon atau tindakan yang mencegah terjadinya aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dapat digunakan PLN untuk berinvestasi.
Pada saat bersamaan, PLN dapat mengurangi subsidi listrik, mendaur ulang asetnya, dan mendapatkan ESG rating yang tinggi.
“Kalau asetnya PLN lebih banyak renewables, itu ESG rating-nya jadi tinggi. Kalau ESG rating-nya bagus, ketika PLN mau pinjam uang di pasar, bunganya akan lebih rendah. Itu kan PLN kalau punya aset fossil fuel tinggi, ESG rating rendah, lenders pasti melihat risikonya tinggi. Walhasil, harus bayar bunga lebih mahal,” ucap Fabby.
Fabby pun berharap pemerintah dapat mengkaji pensiun dini PLTU lebih cermat agar karena jika dihitung berdasarkan strategi bisnis sebetulnya menguntungkan.
“Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya pensiun dini PLTU itu adalah strategi bisnis. Untuk menunjukkan manfaat sebenarnya dari operasi PLTU. Jadi bukan jangan bilang kemudian kita ditekan oleh asing. Itu secara bisnis menguntungkan kok. Hanya sekarang belum ke sana aja mungkin perhitungannya,” katanya.
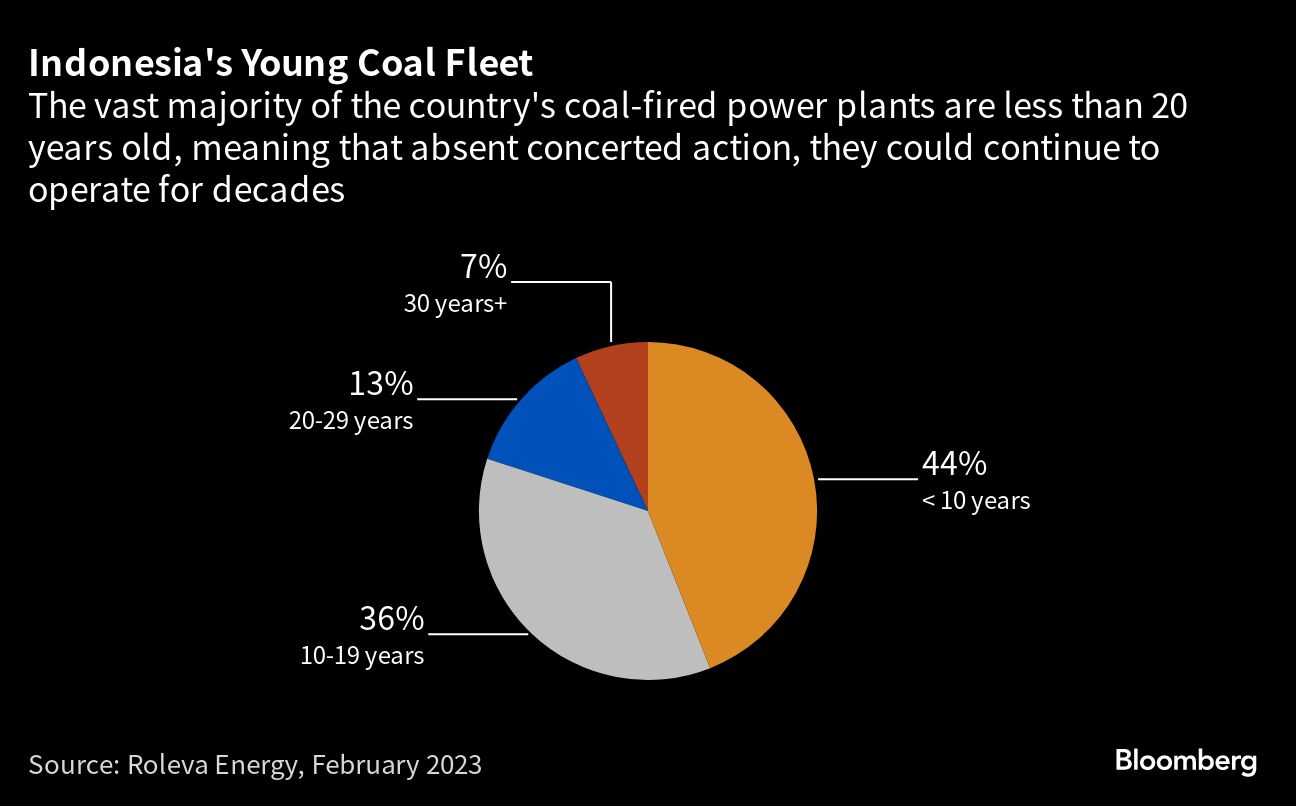
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengisyaratkan pemerintah masih akan terus mengandalkan PLTU berbasis batu bara sebagai penopang kedaulatan energi nasional.
Bahlil juga menolak anggapan bahwa batu bara merupakan sumber energi kotor. Batu bara, menurutnya, bisa disulap menjadi bersih dengan cara menangkap emisi karbonnya untuk dimasukkan ke dalam fasilitas tangkap-simpan karbon atau carbon capture storage (CCS).
Tidak hanya itu, biaya listrik dari pembangkit batu bara juga sangat murah sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menggantikan PLTU sepenuhnya dengan pembangkit-pembangkit berbasis EBT.
Dia menggambarkan biaya listrik per 1 kWh dari batu bara hanya sekitar 5—6 sen, tetapi biaya listrik dari EBT bisa mencapai 9,5—10 sen, bahkan 11 sen.
“Saya menghitung kalau kita pakai gas, 1 GW listrik dengan memakai gas, biaya kemahalannya antara gas dengan batu bara per tahun kurang lebih sekitar Rp5 triliun—Rp6 triliun,” kata Bahlil di sela Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).
Jika digunakan selama 10 tahun, menurutnya, berarti terdapat biaya kemahalan yang harus ditanggung sekitar Rp50 triliun—Rp60 triliun. “Kalau kita konversi menjadi 10 GW, itu berarti 10 kali Rp60 triliun untuk 10 tahun. Rp600 triliun. Itu selisih harga.”
Dia mengumpamakan, jika Indonesia beralih dari PLTU batu bara ke pembangkit gas, negara ini membutuhkan sekitar 20—25 kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk setiap 1 GW kapasitas pemangkitnya.
“Bayangkan kalau 10 GW, berarti tiap tahun kita butuh 250 kargo. Pertanyaan saya, kita memilih yang mana? Memilih gas atau memilih batu bara? Sudah harganya lebih mahal, gas kita kita pakai untuk bakar saja,” ujar Bahlil.
“Saya lebih memilih untuk tetap komitmen pada energi bersih dengan kita blending antara batu bara, gas, dan EBT yang lain, tetapi masyarakat tidak dikorbankan dengan harga yang mahal, dan negara tidak dibebani dengan subsidi. Terserah apa kata orang, tetapi saya harus berpikir tentang rakyat dan negara saya.”
(mfd/wdh)





























