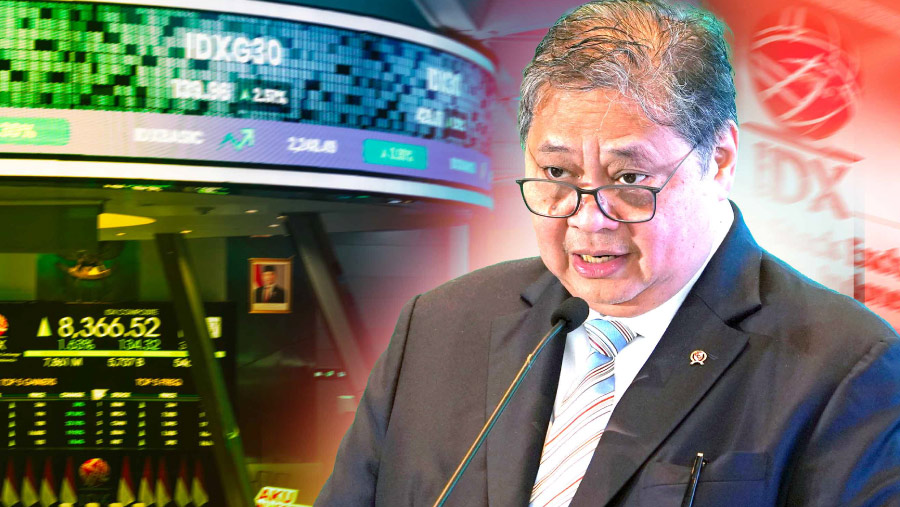“Kalau mau sesuai harapan ya jangan Rp10 ribu. Tapi kalau hanya bisa Rp10 ribu jangan harap sesuai keinginan,” ujarnya.
Ia bahkan menyindir pernyataan tren tersebut dengan kalimat satir, “Mungkin maksudnya Rp10 ribu per menit,” ujarnya sembari menegaskan bahwa kehidupan layak harus tetap mengacu pada standar hidup yang normal.
Menurut Eko, tren seperti ini seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan konteks masing-masing keluarga.
“Harus seimbang antara keinginan dan pengorbanan. Kalau kita pakai dasar UMR, itu sudah jadi acuan standar hidup normal. Jadi, bukan persoalan istri bisa atau tidak, tapi apakah kondisi itu layak dan manusiawi,” tambahnya.
Sementara itu, Psikolog Klinis dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Putri Langka, mengingatkan pentingnya memisahkan dunia media sosial dan dunia nyata.
Ia menyebut, tidak semua tren cocok dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. “Tidak semua hal dalam kehidupan bisa terwakili lewat konten yang sarana dan durasinya terbatas,” ujarnya.
Putri menjelaskan, dari sisi psikologi, persoalan “uang Rp10 ribu” bukan berhenti di nominalnya, tetapi menyangkut perasaan keadilan dan penghargaan dalam hubungan.
“Ketika pasangan dibandingkan dengan figur lain di media sosial, apalagi oleh orang terdekat, muncul perasaan malu, defensif, dan kehilangan rasa aman,” katanya.
Ia menyebut fenomena itu sebagai toxic comparison—kebiasaan membandingkan diri dengan citra ideal di layar yang justru menurunkan kepercayaan dalam hubungan. Menurutnya, dampak perdebatan di dunia maya bisa lebih luas dari yang terlihat.
“Bagi sebagian orang, video itu bisa sekadar hiburan. Tapi bagi yang sensitif secara ekonomi, bisa menimbulkan tekanan emosional. Dalam konteks tertentu, ini bahkan bisa dikategorikan sebagai financial abuse—tekanan psikologis akibat ketimpangan kendali finansial dalam rumah tangga,” terang Putri.
Ia menambahkan, perdebatan soal nominal uang sering memunculkan cognitive distortion, yaitu cara berpikir keliru akibat informasi yang tidak utuh. “Kita sering lupa, yang beredar di media sosial itu opini, bukan fakta. Akhirnya banyak yang menarik kesimpulan ekstrem seperti, ‘kalau begitu lebih baik tidak menikah’, padahal konteksnya tidak sesederhana itu,” ujarnya.
Putri menilai, pelajaran yang seharusnya diambil dari fenomena ini bukan pada besar kecilnya nilai uang, tetapi pada kesadaran dalam menjalaninya. “Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menyadari keterbatasan dengan mindfulness, lalu menjadikannya ruang bersama untuk tumbuh. Karena rumah tangga yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan perbandingan,” pungkasnya.
(dhf)